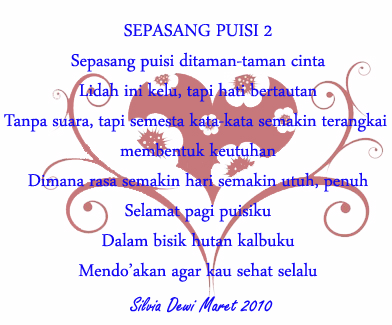IA bernafas dengan harmonika, gamang membayangkan
syair, sajak penyair terakhir, tentang maut & lahir.
Ini seperti balada tentang siapa saja, seperti
petualang menemukan peta pantai hilang, lalu ia
berikrar akan jadi tua, meninggal nama, di sana.
Sebuah lagu akan rampung dihirup-hembuskan, ia
mengecupi harmonika seperti bibir kekasihnya.
Selalu itu membuatnya lebih dalam mematakan pejam.
Ini seperti balada tentang siapa saja, dan itu
berarti yang paling mungkin (dan paling mustahil)
ia akan bernyanyi tak henti tentang Cinta & Sunyi.
Cinta sebab ia telah pernah berani memimpikan mimpi.
Sunyi karena ia tahu akan kembali menjadi sendiri.
Keduanya melahirkan lagu nafasnya pada harmonika,
pada kecup dalam dan lama di lapar bibir kekasihnya.
|
|
|---|
Sunday, August 30, 2009
Balada Siapa Saja
Saturday, August 29, 2009
Catatan 180809
aku mendengar cicak berbisik di dinding, aku mencium aroma waktu berkarat dan kering. gelisah nampak gerimis, berlalu dalam diri yang mendesis.
bau kopi tak mampu mengirim risau ke mulut cangkir. tiktok jam, dan malam sepertiga akhir. mengusung sepi beralamat jauh, sampai ke tingkap paling rapuh...
duh, bayang masakanak. adakah kau mengerti, bila remaja telah mengusaikan kejujuranmu berkata
aku berjalan pada sepi yang menjadi mantel, dan sunyi sebagai isyarat tanpa tanda tanya
aku mengatupkan setiap permenungan ke dalam segala yang tak ada, dan siapa-siapa yang mampu kusebutkan satu persatu, hadir dengan sendiri
aku mendengar cicak kesepian, aku melihat jiwaku yang kesepian, di tengah malam yang retak tanpa simpul
2009
Orang-Orang Bukit Meranti
kirimlah kami cahaya
yang menerangi rumah kami
bila malam menutup
biar tak ada bulan
kami tak akan takut kehilangan
kirimlah kami jalan bagus
untuk hidup kami yang panjang
bila hujan tiba tak ada becek
kami tak akan takut kelaparan
kirimlah kami air bersih
untuk mandi dan mencuci
agar anak-anak kami
tidak kudis dan kurap-korengan
kirimlah kami sinyal telepon
agar kami tahu kabar orang-orang di desa
walaupun sedang mantang balam
kirimlah kami cahaya
kirimlah kami jalan bagus
kirimlah kami air bersih
kirimlah kami sinyal telepon
agar kami mengerti
bahwa zaman adalah sahabat bagi kami
2009
nb : ini adalah hasil pembicaraan dengan orang-orang bukit meranti
suatu masyarakat kecil yang tinggal di pelosok di antara hutan-hutan rimba
di perbatasan desa kertajaya dan desa keramat jaya
mantang balam : menyadap karet
Jangan Ditanya Kenapa Aku Bertanya, X
X.
HUJAN, bagaimana kau menandai jejak
di jalan melingkar perjalananmu?
Bagaimana kau mengatur jadwal kapan
harus turun kapan harus menahan diri?
Kau yang menulis sajak tentang
hujan pernahkah bertanya pada dia
seperti apa harus menuliskan dia?
Tahukah kau bahwa hujan itu tak
tahu apa itu sedih atau murung?
Tahukah kau bahwa hujan itu adalah
kanak-kanak yang rindu bermain?
Tahukah kau bahwa ketika turun, hujan
itu memberi kesempatan matahari untuk
melakukan sesuatu yang rahasia?
Kau yang bosan dengan sajak hujan
tahukah kau bahwa hujan tak pernah
merasa bosan disajakkan?
Friday, August 28, 2009
Jangan Ditanya Kenapa Aku Bertanya, IX
IX.
APA yang dikatakan daun kepada akar yang
tiap hari mengiriminya air dan hara?
Ketika akar pertama tumbuh dari biji
sudahkah ia membayangkan bagaimana kelak
cabang-cabangnya mengatur diri?
Apa yang dikatakan akar kepada batang
yang tiap hari mengantarkan air dan hara
kepada daun?
Siapakah yang paling mencintai buah itu?
Daun, akar, batang, ranting atau tangkai?
Ketika putik jatuh sebelum jadi buah,
siapa di antara mereka yang paling sedih?
Ketika daun mengering, layu dan jatuh,
apa doa yang diucapkan akar untuknya?
Apa pesan rahasia pohon kepada buah yang
matang dan kelak akan jatuh dan tumbuh
sendiri menjadi pohon yang baru?
Altar Sunyi Malam Keseratus
seratus malam aku terlelap. merayapi waktu yang pengap. remaja rampung di sini, kamar yang selalu berbau puisi. seperti penyair abad pertengahan. aku memandang kapal menuju pelabuhan, menunggu kabar yang selalu gantung dari seorang nakhoda. seketika didih gelombang merasuk lewat mimpi panjangku, lewat geladak yang dijaga penumpang, dan kemudi yang melambatkan daratan. aku sendiri merentangkan keduatangan. menghirup bau garam. ada lelah yang terseret di antara suara yang tak mampu menjangkau ujung-ujung kuku. mengendap di penciuman. sepi dan lelah menunggangi garis-garis silam. naluri dari ingatanku terkirim ke suatu negeri tanpa hukum untuk menyelesaikan perkara cinta.
sampai di malam yang terakhir. aku terpelanting di antaran pohon-pohon bakau. hidup diam, dalam kata-kata yang murni sendiri. bahasa telah melupakan sirine kapal dan debur ombak. aku bernyanyi. aku melihat bulan tergantung di antara dahan-dahan ketapang. rimbun dan elok cahayanya. bagai mata ibu yang memintaku untuk berlaku jujur.
ah. alangkah dalam sunyi memanggilku. hingga aku melupakan siapa yang menunggu penuh janji. ( di dalam sunyi tak ada kanak-kanak, tak ada remaja, tak ada dewasa)
yang kutemukan adalah jiwaku menetes ke dalam waktu. roh dan puisi bergandengan menuntunku sampai ke gerbang penghabisan. rahasia dan isyarat tidak ada yang disembunyikan bila makna dapat diterima dengan sederhana. itu adalah ingatanku yang kesekian dari beberapa risalah yang kutemukan di tepian pantai.
/untuk apa kau membalut kata-katamu dengan berlapis-lapis makna. saat semua orang tak mengerti apa maumu. engkau bersorak kegirangan. tidakkah engkau dilahirkan dari sebuah kesederhanaan sikap yang saling mengerti. engkau akan selalu asing bila tak ingin berbagi. ya berbagi saja apa adanya. engkau dapat bercerita tentang petuah-petuah lama dan dongeng-dongeng tua. tentang malaikat yang mengajarimu bersujud. tentang puisi yang beranak pinak dari tangan jadahmu. kemudian kau lepas ia mengembara dicaci-maki atau...o, penyair lugu adakah malam-malam selanjutnya untuk kau akhiri permenunganmu/
di sini segalanya tak memiliki apa-apa
kecuali diriku sendiri yang menuliskan kalimat seperti ini.
2009
Jangan Ditanya Kenapa Aku Bertanya, VIII
VIII.
KENAPA tak ada satu hari saja, semua
peristiwa terjadi sama, sehingga
suratkabar pun terbit dengan isi
yang persis serupa?
Kenapa di zaman nabi-nabi diutus
belum ada suratkabar yang memberitakan
setiap langkah kenabian mereka?
Jika saat kitab-kitab diwahyukan ada
suratkabar apakah setiap ayat yang
turun akan jadi berita utama?
Seandainya para nabi itu adalah pemilik
dan pemimpin redaksi surat kabar,
apa nama suratkabar mereka?
Seandainya nabi-nabi itu berdakwah lewat
suratkabar, apakah suratkabar itu lebih
banyak diedarkan eceran atau langganan?
Apakah di suratkabar para nabi itu juga
ada rubrik tanya jawab surat pembaca?
Jangan Ditanya Kenapa Aku Bertanya, VII
VII.
APAKAH suara azanku dulu di masjid
tua itu masih ada sisa gemanya?
Penjaga tua masjid tua, siapa yang
memugar umurnya bersama pemugaran
masjid yang bertahun-tahun ia jaga?
Kenapa pengeras suara di menara
masjid tua itu tak pernah serak?
Sumur di depan masjid, kalau aku nanti
berwudhu di situ, apakah dia bertanya,
"wah, lama sekali wudhumu tidak batal?"
Ibu, kalau aku azan nanti di masjid
tua itu, apakah kau masih kenal suaraku?
Jangan Ditanya Kenapa Aku Bertanya, VI
VI.
KENAPA ayam betina berkotek
setelah bertelur? Apakah itu
tanda dia gembira atau sedih?
Kokok ayam jantan di waktu subuh,
apakah matahari di sana menyimaknya?
Kalau matahari bicara, apa yang
akan dikatakannya pada ayam yang
berkokok itu?
Kenapa ayam jantan tidak berkokok
juga di tengah hari? Atau petang?
Apakah ayam betina marah karena
terganggu dengan kokok ayam jantan?
Apakah ayam jantan punya kokok yang
khusus di hari-hari yang istimewa?
Apakah ayam jantan berkokok juga
pada hari dia akan disembelih atau
mati terlindas roda kendaraan?
Apakah anak ayam yang masih belum
menetas di dalam telur mendengar
juga suara kokok ayam jantan?
Jangan Ditanya Kenapa Aku Bertanya, IV
IV.
Bisakah lidah diatur hanya mau
mengucap kata-kata Puisi saja?
Bisakah telinga menyaring sendiri
kalimat-kalimat yang didengarnya?
Bisakah mata dibuat memejam sendiri
ketika ada yang tak pantas dilihat?
Kenapa tangan dan kaki hanya bicara
kelak pada Hari Kesaksian saja?
Bisakah tangan diatur hanya mau
memeluk atau berjabatan saja, dan
menolak jika dipakai untuk menampar?
Bisakah mulut membisu sendiri, ketika
dipakai untuk mengucap kata makian?
Jangan Ditanya Kenapa Aku Bertanya, V
V.
SEPASANG kodok plastik mainan masa
kecilku dulu, rindukah mereka padaku?
Maukah kawan-kawanku kuajak bermain
kelereng seperti kanak-kanak kami dulu?
Di manakah dia kini, layang-layang yang
dulu kubuat, lalu putus saat kumainkan?
Lapangan kasti tempat kami bermain
dulu, masihkah dia ingat garis-garis
batas permainan yang kami buat?
Pohon kedondong di depan masjid, kenalkah
ia padaku yang dulu sering memanjatnya?
Kalau aku kembali ke masa lalu, apakah
televisi masih menyiarkan film Si Unyil?
Tahukah muara laut di kampungku, bahwa
dialah yang mengajariku berenang?
Thursday, August 27, 2009
Jangan Ditanya Kenapa Aku Bertanya, III
III
KENAPA cinta itu simbolnya hati merah muda? Kenapa
tidak lingkaran atau segienam, hitam atau putih saja?
Kenapa banyak sekali abjad di dunia ini? Kenapa Tuhan
tidak menetapkan satu abjad saja untuk semua manusia?
Apa jadinya kalau setiap hari orang boleh mengganti
namanya? Atau bolehkah memilih tidak bernama saja?
Kenapa kalau berpisah orang melambaikan tangan?
Tidak adakah isyarat perpisahan lain yang lebih baik?
Kenapa kalau kita menangis keluar air di mata kita?
Kenapa tak keluar cahaya saja? Cahaya mata namanya?
Jangan Ditanya Kenapa Aku Bertanya, II
II
KENAPA kalau gigi susu lepas, tumbuh gigi baru, tapi
kalau gigi dewasa tanggal tak tumbuh gigi baru lagi?
Kenapa gigi harus tumbuh perlahan satu per satu?
Kenapa gigi tidak seperti kuku yang terus tumbuh
dan secara berkala kita harus memotongnya?
Siapa yang memberi tahu gigi supaya dia tumbuh dan
kemudian berhenti sampai ukuran yang sempurna?
Kenapa gigi harus berwarna putih? Tidak merah,
hijau, atau biru? Atau warna emas atau perak?
Berapa banyak gigi mendapat bagian dari zat makanan
yang mereka lumatkan?
Apa perasaan gigi asli ketika berdampingan dengan
gigi palsu yang menggantikan gigi asli yang hilang?
Apa yang dikatakan gusi dan tulang rahang ketika
sebuah gigi terlepas?
Jangan Ditanya Kenapa Aku Bertanya, I
I
KENAPA harus ada kalimat tanya dalam bahasa?
Betulkah ucapan pertama di dunia adalah pertanyaan?
Siapa yang pertama kali bertanya di dunia ini?
Apakah pertanyaan yang pertama kali diajukan?
Kepada siapakah pertanyaan pertama itu ditujukan?
Seberapa banyak pertanyaan di dunia ini yang
terjawab dan seberapa yang tak punya jawaban?
Apakah pertanyaan tak terjawab itu mati penasaran
atau tetap hidup menunggu datang jawaban?
[KOLOM ] Farid Gaban Singgah di Batam
Oleh Hasan Aspahani
Pemimpin Redaksi Batam Pos
Di depannya, malam itu, saya jadi kecil hati bahkan untuk sekadar mengeluarkan Blackberry dari saku. Gadget mahal itu, tiba-tiba menjadi kemewahan yang tak berarti. Dia orang sangat sederhana.
"Tadi kami tidak makan sahur," kata Farid Gaban. Hah? Itu berarti 24 jam lebih dia dan mitra seperjalanannya Ahmad Yunus tidak makan. Sebab, sejak tiba di Batam sekitar pukul empat petang, dalam rangkaian ekspedisi jurnalistik berkeliling Indonesia, dia baru menyentuh makanan saat berbuka bersama Muhamad Nur - Koordinator Liputan Batam Pos, Pemenang Anugerah Adinegoro 2008 yang menjemputnya petang itu di pelabuhan Batuampar.
Malam itu kami mencari tempat makan yang agak istemewa. Pilihannya adalah kelong Aneka Selera di Jembatan IV. Kami makan besar. Sebuah jamuan yang layak untuk 'orang besar' seperti dia.
Di meja restoran terapung yang perlahan naik diangkat oleh pasang laut, terhidang kepiting saos, udang goreng mentega, tumis kangkung belacan, ikan asam pedas, dan aha tentu tak ketinggalan gonggong rebus! Ini buka puasa yang terlambat. Maka, semuanya habis kami lahap berlima: dua wartawan "gila" itu, saya, Muhamad Nur dan Sultan Yohana (yang tak menyesal membatalkan acara memasak sendiri di rumahnya untuk hidangan berbukanya hari itu).
"Yunus, malam ini kita tak perlu sahur lagi," kata Farid Gaban, bersemangat menyuap nasi, lalu membongkar isi otak di balik cangkang kepiting. Saya lihat dia dua kali menambah nasi. Sejak sebelum makan, dia bahkan sudah juga memesan kopi. Di kelong itu kami bertahan ngobrol sampai agak malam. Dari musala yang entah dimana, terdengar takbir dan salawat jamaah tarawih.
***
Ini memang sebuah ekspedisi "gila". Seorang wartawan senior yang di Indonesia sudah lazim diketahui reputasi dan dedikasinya, ditemani seorang wartawan muda yang ideologi jurnalismenya diasah di Pantau - sebuah majalah dan kemudian menjadi komunitas penganut nilai-nilai tinggi jurnalistik.
"Semula ekspedisi ini dirancang bersama sebuah sponsor. Ketika rencana itu batal, saya bilang ke mereka, saya akan jalan meskipun tanpa mereka," kata Farid memulai cerita.
Farid adalah perencana yang handal. Ini mungkin ada kaitannya dengan latar pendidikannya. Dia kuliah mendalami kekhususan Tata Kota ITB, meskipun tidak sempat menyelesaikan penulisan skripsi yang membandingkan dua ruas jalan di Malang dan Bandung.
Maka dirancanglah ekspedisi jurnalistik yang ia bayangkan akan menyinggahi seratus pulau di Indonesia. Biayanya Rp120 juta. Semula ini akan ditutup dari uang penjualan feature hasil perjalanan itu dengan sistem sindikasi.
Tapi, sistem sindikasi itu ia sadari belum terlalu lazim di Indonesia. Akhirnya hanya Republika dan Majalah Tempo yang membeli hak menerbitkan beberapa tulisnya. Tentu saja itu tak cukup untuk membiaya ekspedisi ini.
Lalu dari mana dana itu didapat? "Jual buku," katanya. Farid betul-betul mempersiapkan diri. Ia membeli kamera mahal, notebook (di Mentawai kedua benda wajib ini tercebur ke laut dan dia harus membeli yang baru), dua motor Win 100 CC yang dirombak menjadi a la trail (tapi tetap saja paling banter hanya bisa dikebut 80 km per jam), dan dia ambil sertifikat menyelam. "Saya banyak memotret terumbu karang," katanya.
Ya, mata kameranya dipesiapkan untuk banyak menangkap kepermaian lingkungan alam, dan dinamika manusia dan Indonesia. Sebuah penerbit sudah berkomitmen menerbitkan empat buku berisi foto-foto hasil jepretannya itu. Ia dan timnya juga berharap kelak bisa menjual hasil rekaman video dari perjalanan itu.
***
Farid Gaban sudah menjadi wartawan sejak ia kuliah di Bandung. "Saya mulai dulu sebagai reporter di Tempo Biro Bandung," katanya.
Saya mengenal namanya, menikmati, mengagumi dan belajar dari tulisan-tulisannya ketika dia bergabung dengan Republika. Waktu itu saya sudah mahasiswa. Di koran yang pada masa awal terbit membawa angin baru dalam atmosfer pers Indonesia, dia menulis kolom yang bagus. Solilokui namanya. Kelak kumpulan kolom itu dibukukan dibawah judul "Belajar Tidak Bicara".
Di kolom itu ia menulis dengan logika yang mengejutkan, ide yang tak terpikirkan dan bahasa renyah karena sederhana. Ia misalnya menulis tentang betapa absurdnya sepatu. Ia melindungi kaki tetapi ketika memakai sepatu kita harus melindungi kaki dengan kaus kaki, sebab sepatu yang melindungi itu bisa melecetkan kaki. Malam itu saya pastikan dia memang tidak memakai sepatu, kecuali sepatu sandal.
Ia juga pernah mengadaptasi tulisan Simon Carmiggelt, kolomnis Belanda tentang peri junior yang dimarahi peri senior sebab tak bisa mengabulkan permintaan seseorang yang telah menyelamatkannya, karena permintaan sederhana "turunkan harga" harus dilakukan dengan rumitnya sistem ekonomi modern. Dia salah satu kolomnis terbaik yang pernah ada di Indonesia.
Ya, dia Farid Gaban. Dia adalah salah seorang yang diam-diam membuat saya makin yakin untuk menjadi wartawan. Dia pernah meliput di Bosnia, Afghanistan, juga Piala Dunia di Amerika. Malam itu saya bersama dia. Terus terang saya agak gugup dengan pertemuan itu. Ha ha ha. Seperti kencan pertama rasanya. Saya bertambah kagum karena ternyata betapa sederhana dan bersahajanya dia. Tubuhnya tak terlalu besar, kulitnya menghitam, pasti karena terbakar matahari selama perjalanan bermotor yang ia mulai sejak Juni 2009 itu.
"Saya mundur sebagai Redaktur Eksekutif karena saya tak setuju ketika waktu itu Republika memilih Harmoko sebagai Man of The Year," katanya ketika saya tanya kenapa keluar dari surat kabar yang kala itu dipimpin Parni Hadi. Ia mengucapkan kalimat itu dengan nada biasa saja, tanpa kesan melebih-lebihkan, menonjolkan idealisme, atau menyombongkan diri.
Ia kemudian bergabung kembali dengan Tempo dan sempat mengomandani divisi Investigasi dan menghasilkan liputan-liputan yang sedikit mengguncang stabilitas penguasa.
Ketika ia menjadi pejabat redaksi (menjadi redaktur pelaksana), yang tak lagi banyak memikirkan liputan ia tak betah. "Saya digaji mahal tapi saya merasa saya tak melakukan apa-apa," katanya. Padahal jiwanya adalah di lapangan. Dia terpanggil untuk meliput, melakukan reportase.
"Pekerjaan liputan masih sangat menarik buat saya," katanya. Sungguh, jika engkau benar-benar wartawan, kalimat sederhana itu akan telak menampar jiwamu. Itu yang mungkin mendorongnya untuk menuntaskan ekspedisi yang rutin dia laporkan di situs zamrud-khatulistiwa, menyamakan dengan nama ekspedisi yang kelak berakhir Desember nanti.
***
Ada yang salah dengan Indonesia. Itulah premis yang ada di kepala Farid dan tim pendukung ekspedisinya itu. Negara dengan 17 ribu pulau ini dibangun tanpa berorientasi pada lautan. Indonesia dibangun dengan perhatian penuh pada kota dan daratan, melupakan pulau-pulau kecil dan laut dengan segala potensinya. Padahal, lautanlah yang dia yakini menyelesaikan banyak persoalan di negeri ini.
"Sebenarnya perjalanan ini kan hanya mengkonfirmasi apa yang kita yakini itu," katanya. Dan itulah yang dia temukan.
Pedih sekali sepertinya ketika mendengar ia mengatakan, "tak ada tempat yang kami kunjungi yang tak subur. Laut kita kaya, tapi tak ada tempat yang tak ada orang miskinya. Memang ada yang salah besar dari cara berpikir kita di Indonesia ini."
Batam, adalah bagian dari 100 pulau yang akan dia singgahi. Dia lalu menyeberang ke Tanjungpinang, Lingga, Tambelan, Anambas, Natuna, dan lalu ke Kalimantan. Saya sangat ingin tahu apa yang kelak ia tulis tentang Provinsi Kepulauan Riau ini. Di Batam, malam itu, dia mengagumi jalan-jalan yang lebar dan mengunjungi beberapa tempat. Ia memotret kebun buah naga, dan singgah di kamp pengungsi di Pulau Galang.
***
Bagi saya, Farid adalah manusia pencinta manusia dan kemanusiaan. Ia bercerita tentang manusia-manusia kecil yang ia temui dan ia tulis dalam feature perjalanannya.
Ia tak terlalu silau pada kekuasaan, dan itu sebabnya ia amat kritis pada penguasa. Ia menolak keras kenaikan harga minyak, sebab kebijakan itu hanya memikirkan orang-orang di Jakarta. Hal itu makin ia yakini, setelah melihat sendiri di Enggano sebotol bensin harganya bisa berkali-kali lipat, dan orang miskin di sana tak punya pilihan selain membeli semahal apapun.
Saya tak tahu, apakah ini keinginan lama ataukah muncul setelah ia melihat betapa suburnya tanah-tanah di negeri ini. Ketika saya bertanya apa rencananya selanjutnya, saya tertegun dengan jawabannya, "Setelah ekspedisi ini saya ingin pulang ke Wonosobo. Menetap di sana, jadi petani," kata Farid.
Wednesday, August 26, 2009
lonely-lonely road...
yang berdiam diri
seribu kali meratapi
berpasrah menepi..
menghindari peri peri
menyambut pagi lagi
bilang padanya aku mampu menari
tanpa sendumu aku bebas bergemuruh
mati tetap ada di hati
tapi pergilah jauh
pelangi mewarnai warna-warna hati
suka cita lonely-lonely road
menapaki lonely-lonly road
by:1+03Zz
Kamu Pastinya Tau
kamu pastinya tau
malam itu gelap
sehingga kamu takut untuk keluar
kamu juga pastinya tau
jatuh itu sakit
sehingga kamu selalu berhat-hati
tapi...
kamu harus sadar
siang yang terang
mengintip menantimu dalam kebahagiaan
kamu juga harus mengerti
sakit itu mengajarkanmu
mengantarkan pada lembah
kesuksesan yang kau nantikan
kata-katamu sungguh sangatlah bijak...
hingga mampu membuatku masuk pada bait-bait syair cinta yang kau tuliskan dengan penuh penghayatan...
makasih ya...???
ku yakin,diluar sana banyak sekali yang lebih baik yang bisa ngebahagiain kamu sambih mengemis-ngemis memohon cintamu...
salam kwnal aza dari aku..
"Puisi yang dikirim oleh Mas Said pada komentar salah satu puisi blogs ini"
Hati yang Terluka
Wahai, hati yang terluka...
Bacakanlah semua itu dalam keharibaanNya...
Dan katakan kepadaNya: semua ini ku pasrahkan kepada Mu...
Untuk orang bodoh yang membuat Dia terluka....
Tidak sepatutnya Kau mendapatkan untaian tabir hati itu...
Dan alangkah tinggi derajat mu, walaupun kau menyakiti...
Wahai, hati yang terluka...
Sekarang torehkan lembaran baru dalam sajak berjudul "Yang Terbaik Bukanlah Dirimu"....
Dan hapuslah coretan merah dalam perjalanan mu itu..
Niscaya esok hari mimpi dan keinginan mu tertata lebih baik...
"Puisi ini aku ambil dari komentar teman di http://toppuisi.blogspot.com/2009/05/akhir-cerita.html#comments"
Quinta Tangis
KAU yang menangis karena tak tahu kenapa kau berdoa untukku
Aku menangis karena tak tahu bagaimana mengaminkan doamu
Kau tak menangis karena duka tapi bertanya apakah aku menangis?
Aku tak menangis tapi ingin sekali menangis ketika kau bertanya
Adapun Tuhan? Dia mengerti doa kita dan mengabulkan tangis kita.
Tuesday, August 25, 2009
Untuk Penyair yang Mati, juga untuk Siapa Saja
KEMATIAN itu, Tuan, adalah juga
kesaksian atas kehidupan, bukan?
Sunday, August 23, 2009
Doa, 3
Orang kerdil ini, Oh, betapa besar inginnya hati,
dua tadah tangan, bukan wadah bagi kecukupan
Allah-ku, pinjam aku tangan-Mu menggenggamku. Amin.
Doa, 2
Allah-ku, aku rasa Engkau tak perlu banyak beri waktu untukku.
Kefanaanku, kefanaanku, rindu bertemu dengan kebaqaan-Mu
Aku - fana waktu - mau mengekal bersama-Mu, Allah-ku. Amin.
Doa, 1
Allah-ku, segerakanlah datang siksa atasku
Timpakanlah azab padaku selekas-lekasnya
atas segala lupa, lalai, dosa dan ingkarku
Asal itu tak menjauhkan aku dari-Mu. Amin.
Friday, August 21, 2009
Ada Anak Bertanya
ADA anak bertanya pada
laparnya, "Sampai kapan
engkau ada di tubuh kami
yang selalu saja puasa?"
Lapar, yang tak pernah
benar-benar bisa pergi
dari anak seperti anak
yang selalu puasa, yang
bertanya padanya itu tak
tahu harus menjawab apa.
Ia terlalu sayang pada
kurus tubuh anak itu, "ini
sudah seperti tubuhku
sendiri," kata lapar itu.
Pancasila?
1. Ketuhanan yang Mahaesa?
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab?
3. Persatuan Indonesia?
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaaan dalam permusyawaratan /perwakilan?
5. Keadilan sosil bagi seluruh rakyat Indonesia?
[FIKSIMINI] Siluman
si·lu·man 1 n makhluk halus yg sering menampakkan diri sbg manusia atau binatang; 2 ki a tersembunyi tidak kelihatan: pasukan --; biaya -- , biaya yg sulit dipertanggungjawabkan (spt uang suap dsb)
"SAYA bosan jadi makhluk halus yang harus menyamar jadi siluman terus," kata siluman itu padaku, "tapi apa saya harus jadi manusia? Atau jadi binatang? Apa tak ada pilihan lain? Anda punya saran?"
Setahu saya, karirnya sebagai siluman lumayan baik. Dia (makhluk halus ini) pernah menyilumankan diri menjadi serigala, babi, anjing, dan ular. Pilihan untuk jadi apa itu tergantung order manusia yang perlu jasa siluman. Tetapi, dia (makhluk halus ini) tidak pernah mau menyiluman menjadi manusia, walaupun di Kamus Besar Bahasa Indonesia siluman itu bisa juga menampakkan diri sebagai manusia.
"Buat apa? Manusia itu lebih siluman dari siluman, kok!" katanya padaku dulu, ketika saya sebagai calo menghubungi dia menyampaikan order dari seseorang yang ingin dia (makhluk halus ini) menyiluman menjadi manusia. Saya mengingatkan dia (makhluk halus ini) percakapan kami dahulu itu.
"Berarti sudah jelas, kau tak mau jadi manusia, kan?" kata saya padanya.
"Oh, ya, saya ingat percakapan kita itu. Tapi, kau salah. Saya kira saya akan jadi manusia saja. Saya yakin sebagai mantan makhluk halus yang sering diminta jadi siluman oleh manusia yang lebih siluman dari siluman, nanti saya pasti akan jadi manusia yang baik," katanya. ***
Read More...
[FIKSIMINI] Mahasiswa
ma·ha·sis·wa n orang yg belajar di perguruan tinggi; ke·ma·ha·sis·wa·an n seluk-beluk mahasiswa; yg bersangkutan dng mahasiswa: kuliah kerja nyata (KKN) tidak dapat dipisahkan dr kegiatan -
: M Aan Mansyur
DIA selalu bilang bahwa dia kuliah di Fakultas Kehidupan, Jurusan Puisi atau bisa juga sebaliknya Fakultas Puisi, Jurusan Kehidupan.
"Bukan, bukan di Jurusan Sastra, Fakultas Ilmu Budaya," katanya, setiap kali ditanya soal di mana dia menuntut ilmu di perguruan tinggi itu.
"Itu dulu, saya memang pernah tersasar ke sana. Waktu itu saya hanya bisa memanjangkan rambut saya dan mencuri beberapa halaman dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Waktu itu saya hanya bisa menulis sajak dengan huruf yang tak cukup dan sajak-sajak yang terburu-buru," katanya.
"Oh, begitu ya?" tanya saya, "jadi kapan kau sudah dinyatakan lulus dan apa gelar yang berhak kau sandang di depan atau di belakang namamu?"
"Hah? Apa? Lulus? Gelar? Ini adalah kuliah yang abadi, Bung, kerja yang sungguh tidak nyata! " dia lantas tertawa-tawa, lalu menangis, lalu tertawa lagi. Saya tak mengerti, apa maksudnya. Sungguh, saya tak mengerti. ***
Read More...
[FIKSIMINI] Puisi
pu·i·si n 1 ragam sastra yg bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait; 2 gubahan dl bahasa yg bentuknya dipilih dan ditata secara cermat sehingga mempertajam kesadaran orang akan pengalaman dan membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan makna khusus; 3 sajak;...
DIA marah sekali pada para penyusun kamus yang tak dikenalnya itu. "Cuma begitu kemampuan mereka menguraikan makna diriku? Huh! Memalukan. Memuakkan!" katanya.
"Sabar. Sabar..." kata saya mencoba menyabarkan dia.
"Sabar? Apa saya bisa sabar? Coba kamu baca itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi apa itu? Ragam sastra yang bla bla bla...., gubahan dalam bahasa yang bla bla bla... Apa itu?" katanya, marahnya makin menjadi.
"Eee, begini sajalah. Biar saya yang bukan siapa-siapa ini mencoba mendefinisikan kamu dengan cara lain. Yaitu dengan terus-menerus mencoba menuliskan Anda. Bagaimana?" kata saya.
Sepertinya marahnya mereda. Dia lalu pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tapi, rasanya dia tak pernah berada terlalu jauh dari saya. Saya, menyesal juga sudah menjanjikan sesuatu padanya. Karena sejak saat itu saya selalu merasa tertagih, terus-menerus menuliskan dia....
Read More...
[FIKSIMINI] Tidak
ti·dak adv partikel untuk menyatakan pengingkaran, penolakan, penyangkalan, dsb; tiada: tempat kerjanya -- jauh dr rumahnya; apa yg dikatakannya itu -- benar; ...
"OH, tidak! Seharusnya aku tidak ada di sana, di halaman kamus ini. Tidak! Seharusnya tak usah saya dilemakan di sini!" kata kata "tidak" itu.
Saya memperhatikan kata itu. Sudah sering saya bertemu dia di sana, ketika sesekali saya berkunjung ke sana, ke Kamus Besar Bahasa Indonesia itu. Tapi, kali ini saya lihat dia lain...
"Oh, sayalah kata yang merusak segalanya. Sayalah kata yang menggoda pasangan manusia pertama itu terbuang dari surga dan kemudian menjalani kehidupan lain di dunia. Aduh, maafkan saya, saya sebenarnya tak pernah ingin lahir sebagai 'tidak', sebagaimana kini adanya saya! Sayalah yang dulu meminta Hawa mengucapkan saya, sekali saja, itulah saat saya pertama kali diucapkan, yaitu ketika Hawa mengajak Adam menidakkan larangan itu..."
Saya tak tahu apakah dia berbicara pada saya. Saya menyimak dan mulai mengerti kenapa dia bicara seperti menahan menangis, seakan menanggung sesuatu yang amat besar sesalnya...
"Saya bukan antonim dari 'ya'. Bukan. Saya tak pernah melawan dia. Saya dulu adalah bagian dari dia. Saya menghormati dia. Saya mengagumi dia. Saya salut pada ketabahan 'ya' kata paling hebat di dunia itu. Saya ini tidak ada apa-apanya dibanding dia. Oh, betapa inginnya saya kembali lagi menyatu dengannya...."
Ah, kata yang cengeng. Saya balikkan saja halaman kamus itu. Mencari kata lain.***
Read More...
[FIKSIMINI] Kamus
ka·mus n 1 buku acuan yg memuat kata dan ungkapan, biasanya disusun menurut abjad berikut keterangan tt makna, pemakaian, atau terjemahannya; 2 buku yg memuat kumpulan istilah atau nama yg disusun menurut abjad beserta penjelasan tt makna dan pemakaiannya; 3 ki diri, pikiran: tak ada istilah “takut” dl -- saya;
"BILANG pada Penyair itu --- ah, siapa namanya itu? --- Apa salah saya? Saya tak pernah membelenggu kata manapun. Saya tak pernah meminta kata-kata itu ada di dalam saya.
"Saya sayang pada semua kata-kata yang ada pada saya. Ada kata yang tak pernah lagi kalian perhatikan. Ada yang mati terbunuh. Ada kata yang entah bagaimana kalian memperlakukannya, tiba-tiba dia merasa bukan lagi kata...
"Jadi, jangan salahkah saya. Tolong, bilang pada Penyair itu --- ah, siapa itu namanya -- ya. Tak perlu dia membebaskan kata dari saya, saya tak pernah membenahi kata manapun. Saya ini kan cuma menampung kata. Menerima tumpangan. Menerima mereka apa adanya...
"Jadi, jangan musuhi saya. Bilang padanya, pada Penyair itu, dia bebas saja membebaskan kata yang mana saja dari saya. Pada hakikatnya kata-kata itu memang bebas, bukan? Jangan terlalu menganggap saya ada. Saya ini apalah, saya cuma kamus saja." ***
Read More...
Tuesday, August 18, 2009
Event Sastra
Temu Sastrawan Indonesia II: Sastra Indonesia Pascakolonial, 30 Juli-2 Agustus 2009
Mencari Identitas Sastra Indonesia
Sastra moderen Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perpanjangan dan politik kolonial Belanda dengan keberadaan Balai Pustaka-nya pasca lingua franca, bahasa Melayu menjadi bahasa administratif pemerintahan lewat pengajaran di sekolah. Keberadaan sastra moderen Indonesia sebagai sastra pascakolonial, tentu berbeda dengan sastra pascakolonial di negara-negara Dunia Ketiga lainnya. Masing-masing memiliki ciri khas dan problemnya sendiri. Sastra Indonesia berbeda dengan sastra Amerika Latin, sastra Afrika, atau sastra negara-negara Asia bekas jajahan Barat lainnya. Sebagai bekas jajahan Belanda misalnya, kita tak pernah meneruskan bahasa Belanda sebagai ekspresi (sastra) kita, berbeda dengan kalangan sastrawan hibrid India, yang menulis dalam bahasa bekas jajahannya (Inggris).
Lantas, apakah yang disebut dengan sastra Indonesia itu sastra yang yang berbahasa Indonesia, atau ditulis oleh orang Indonesia, ataukah sastra yang berisi segala sesuatu tentang Keindonesian? Bagaimana pula posisi sastra berbahasa daerah, atau sastra populer yang dalam sejarahnya juga bagian dari sastra alternatif?
Persoalan di atas menjadi garis besar yang diangkat dalam Temu Sastrawan Indonesia II di Pangkalpinang, Propinsi Bangka Belitung, pada 30 Juli-2 Agustus 2009. Dengan tema “Sastra Indonesia Pascakolonial”.
Dalam diskusi sesi 1, Jum'at (31 Juli 2009), dengan tema “Merumuskan Kembali Sastra Indonesia: Definisi, Sejarah, Identitas” dengan pembicara Agus R. Sarjono, Saut Situmorang, Haryatmoko dan moderator Joni Ariadinata.
Menurut Agus R Sarjono, Sastra Indonesia didominasi oleh gambaran rumah yang hilang, retak, hancur, atau tak tergapai. Maka hampir dapat disimpulkan bahwa selepas kolonialisme para sastrawan Indonesia sebagian besar tak berumah. Kajian atas pewacanaan lahirnya bangsa sebagaimana direpresentasikan dalam novel Keluarga Gerilya Pramoedya Ananta Toer dan Jalan Tak Ada Ujung Mochtar Lubis, berakhir pada kesimpulan bahwa Indonesia adalah sebuah negeri tanpa rumah.
Saut Situmorang yang mengusung “Politik Kanon Dalam Sastra Indonesia: Beberapa Catatan” sebagai bagian persoalan dari definisi, sejarah, identitas sastra Indonesia, melihat adanya ketidakjujuran dalam peta sastra Indonesia. Kepentingan yang tidak lepas dari nilai “politik” suatu kelompok. Misalnya karya sastra yang dianggap sebagai Kanon tanpa melalui sebuah kritik sastra yang pantas.
“Pada umumnya politik kanonisasi sastra diyakini lebih banyak dipengaruhi oleh politik kekuasaan demi kepentingan ideologis, politis dan nilai-nilai ketimbang sekedar karena kedahsyatan artistik karya. Pada saat yang sama politik kanonisasi sastra juga membuktikan betapa naifnya, betapa ahistorisnya, betapa tidak membuminya, para sastrawan yang masih yakin bahwa teks sastra adalah segalanya, bahwa tidak ada apa-apa di luar teks sastra, apalagi yang bisa mempengaruhi eksistensinya, bahwa 'substansi' sastra adalah ukuran karya sastra, karena 'substansi' adalah 'estetika' sastra yang 'sublim', sastra yang menjadi itu,” ujarnya.
Apa yang disampaikan oleh tiga pembicara di atas bukanlah jawaban final dari permasalahan sastra Indonesia yang berlarat-larat dengan eksistensinya. Akan tetapi, memberikan ruang bagi pertanyaan-pertanyaan dalam perjalanan sastra Indonesia, dulu-sekarang-dan akan datang.
Begitu pula pada Diskusi Sesi II di hari yang sama.
Mengambil tema “Kritik Sastra Indonesia Pascakolonial” dengan pembicara Dr. Syafrina Noorman, Yasraf Amir Piliang, Katrin Bandel, Zen Hae, dan moderator Willy Siswanto. Pertanyaan tentang identitas sastra Indonesia itu menukik pada persoalan 'keberadaan' kritik sastra yang kurang dari khazanah sastra Indonesia.
Yasraf Amir Piliang berpendapat, tugas kesusasteraan masa depan adalah membangun 'imajinasi' mandiri (self imagination), dengan meninggalkan 'imajinasi-imajinasi kolonial' atau imajinasi produksi 'sang lain', untuk mampu menghasilkan 'perbedaan' dan 'otentisitas', melalui sebuah sebuah proses 'menjadi diri sendiri' (becoming one-self). Dunia sastra diharapkan mampu membangun sebuah proses pertandaan (signification) yang melaluinya tanda-tanda budaya-budaya diperbedakan, makna-makna diproduksi, dan nilai-nilai dikembangkan. Sebuah proses 'resemiotasi' kebudayaan (cultural re-semiotizatian) melalui kekuatan sastra dapat diusulkan, dalam rangka pengkayaan dan penganekaragaman bentuk, makna dan nilai-nilai kebudayaan itu sendiri.
Pada hari ke dua, Sabtu (1 Agustus 2009), Diskusi Sesi III “Membaca Teks dan Gerakan Sastra Mutakhir: Mencari Subjek Pascakolonial” dengan pembicara Nenden Lilis Aisyah, Nurahayat Arif Permana, Zurmailis, Radhar Panca Dahana dan moderator Triyanto Triwikromo.
“Dalam perkembangan sastra kita pada era yang untuk sementara secara simplis saya sebut era reformasi ini, tema karya sastra cukup beragam. Namun, di antara tema-tema tersebut ada tema yang mendapat banyak sorotan. Tema yang dimaksud adalah tema mengenai femisme, dan tema seksualitas dan tubuh. Sorotan itu terjadi karena; pertama, radikal dan berani; kedua, karena dianggap ideologi barat,” ucap Nenden Lilis Aisyah.
Dikusi yang semustinya menarik—merujuk pada tema yang dihadirkan—terasa agak hambar. Selain pembicara yang kurang mampu menghidupkan diskusi, juga banyaknya kursi peserta yang kosong.
Sementara pada Diskusi Sesi IV, “Penerjemah Sastra Muktahir: Mencari Subjek Pascakolonial” dengan pembicara Anton Kurnia, Arif Bagus Prasetyo, John McGlym dan moderator Tia Setiadi.
Menurut Arif Bagus Prasetyo, penerjemahan adalah kegiatan yang amat kompleks. Bahasa itu sendiri sudah kompleks, tapi faktor-faktor yang terlibat dalam wacana manusia bahkan lebih kompleks. Tujuan terjemahan begitu beragam, dan pembaca karya terjemahan juga sangat beragam. Rasanya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa penerjemahan, mengutip pakar studi terjemahan, I. Richards, barangkali jenis peristiwa paling kompleks yang dihasilkan dalam evolusi jagad raya.
“Betapa memprihatikan kondisi karya terjemahan kita secara umum. Di antara sejumlah karya terjemahan yang bisa dibilang baik, amat banyak karya terjemahan yang buruk. Menurut Alfons yang pernah menjadi Ketua Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI), para penerjamalah yang paling bertanggung jawab atas kualitas karya terjemahan mereka. Namun, ia pun mengakui adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seorang penerjemah, seperti situasi sosial ekonomi, akses terhadap refrensi, serta penghargaan orang terhadap penerjemah dan hasil karyanya,” tutur Anton Kurnia.
Sementara John McGlynn dari Yayasan Lontar menilai tentang usaha penerjemahan Sastra Indonesia ke dalam bahasa Inggris, memiliki beberapa hambatan, yaitu kwalitas karya, ongkos penerbitan, sikap xenofobis, dan kurangnya visi pemerintah.
“Sebagaimana halnya dengan Indonesia yang mendapatkan hikmah dari pengetahuan mengenai kebudayaan lain, negara-negara lain dapat memperoleh manfaat dari ilmu yang berasal dari Indonesia—sebuah hal yang tidak akan terjadi kecuali orang Indonesia dapat mempromosikan diri secara aktif,” tukasnya.
Di mana Identitas Sastra Indonesia?
Selain Diskusi Sastra, TSI II 2009 yang dihadiri oleh pelaku sastra (Sastrawan dan Penikmat Sastra) dari berbagai wilayah yang ada di tanah air—yang setidaknya mewakili kantung sastra, baik muda mapun tua dalam proses kreatif—juga diisi dengan malam Apresiasi Sastra dan pertunjukan pembacaan karya sastra, peluncuran buku antologi sastra “Pedas Lada Pasir Kuarsa” (kumpulan puisi TSI II 2009) dan “Jalan Menikung ke Bukit Timah” (kumpulan cerpen TSI II 2009), Bazar Buku, dan Wisata Budaya.
Sudahkah identitas sastra Indonesia ditemukan? Terlalu naif jika dalam 4 hari untuk menagihnya. Peristiwa sastra di pulau Timah itu, barangkali bisa jadi 'modal' untuk menggali sastra Indonesia 'lebih' dan merangsang proses kreatif sastrawan. Di mana sastra Indonesia tidak sekedar selesai sebagai 'teks' semata dan tidak ada apa pun di luar 'teks' itu—hal ini bisa kita lihat dari penghargaan karya sastra yang ada, bahkan sekelas Nobel pun!--sebab omong kosong yang indah apabila sastra terbebas dari nilai di luar sastra itu sendiri. Sehingga ketika karya (sastra) selesai ditulis, pengarang cukup berleha-leha saja gara-gara salah kaprah memahami istilah, “pengarang sudah mati”.
Namun, bagaimana event sastra seperti Temu Sastrawan Indonesia itu tidak dijadikan sekedar sebuah pesta laiknya beberapa event sastra di Indonesia yang konon katanya bertaraf internasional. Bukan ajang 'bersolek' para sastrawan semata. Inilah tantangan bagi penyelenggara Temu Sastrawan Indonesia berikutnya 2010 di Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau.
Event Sastra
Temu Sastrawan Indonesia II: Sastra Indonesia Pascakolonial, 30 Juli-2 Agustus 2009
Mencari Identitas Sastra Indonesia
Sastra moderen Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perpanjangan dan politik kolonial Belanda dengan keberadaan Balai Pustaka-nya pasca lingua franca, bahasa Melayu menjadi bahasa administratif pemerintahan lewat pengajaran di sekolah. Keberadaan sastra moderen Indonesia sebagai sastra pascakolonial, tentu berbeda dengan sastra pascakolonial di negara-negara Dunia Ketiga lainnya. Masing-masing memiliki ciri khas dan problemnya sendiri. Sastra Indonesia berbeda dengan sastra Amerika Latin, sastra Afrika, atau sastra negara-negara Asia bekas jajahan Barat lainnya. Sebagai bekas jajahan Belanda misalnya, kita tak pernah meneruskan bahasa Belanda sebagai ekspresi (sastra) kita, berbeda dengan kalangan sastrawan hibrid India, yang menulis dalam bahasa bekas jajahannya (Inggris).
Lantas, apakah yang disebut dengan sastra Indonesia itu sastra yang yang berbahasa Indonesia, atau ditulis oleh orang Indonesia, ataukah sastra yang berisi segala sesuatu tentang Keindonesian? Bagaimana pula posisi sastra berbahasa daerah, atau sastra populer yang dalam sejarahnya juga bagian dari sastra alternatif?
Persoalan di atas menjadi garis besar yang diangkat dalam Temu Sastrawan Indonesia II di Pangkalpinang, Propinsi Bangka Belitung, pada 30 Juli-2 Agustus 2009. Dengan tema “Sastra Indonesia Pascakolonial”.
Dalam diskusi sesi 1, Jum'at (31 Juli 2009), dengan tema “Merumuskan Kembali Sastra Indonesia: Definisi, Sejarah, Identitas” dengan pembicara Agus R. Sarjono, Saut Situmorang, Haryatmoko dan moderator Joni Ariadinata.
Menurut Agus R Sarjono, Sastra Indonesia didominasi oleh gambaran rumah yang hilang, retak, hancur, atau tak tergapai. Maka hampir dapat disimpulkan bahwa selepas kolonialisme para sastrawan Indonesia sebagian besar tak berumah. Kajian atas pewacanaan lahirnya bangsa sebagaimana direpresentasikan dalam novel Keluarga Gerilya Pramoedya Ananta Toer dan Jalan Tak Ada Ujung Mochtar Lubis, berakhir pada kesimpulan bahwa Indonesia adalah sebuah negeri tanpa rumah.
Saut Situmorang yang mengusung “Politik Kanon Dalam Sastra Indonesia: Beberapa Catatan” sebagai bagian persoalan dari definisi, sejarah, identitas sastra Indonesia, melihat adanya ketidakjujuran dalam peta sastra Indonesia. Kepentingan yang tidak lepas dari nilai “politik” suatu kelompok. Misalnya karya sastra yang dianggap sebagai Kanon tanpa melalui sebuah kritik sastra yang pantas.
“Pada umumnya politik kanonisasi sastra diyakini lebih banyak dipengaruhi oleh politik kekuasaan demi kepentingan ideologis, politis dan nilai-nilai ketimbang sekedar karena kedahsyatan artistik karya. Pada saat yang sama politik kanonisasi sastra juga membuktikan betapa naifnya, betapa ahistorisnya, betapa tidak membuminya, para sastrawan yang masih yakin bahwa teks sastra adalah segalanya, bahwa tidak ada apa-apa di luar teks sastra, apalagi yang bisa mempengaruhi eksistensinya, bahwa 'substansi' sastra adalah ukuran karya sastra, karena 'substansi' adalah 'estetika' sastra yang 'sublim', sastra yang menjadi itu,” ujarnya.
Apa yang disampaikan oleh tiga pembicara di atas bukanlah jawaban final dari permasalahan sastra Indonesia yang berlarat-larat dengan eksistensinya. Akan tetapi, memberikan ruang bagi pertanyaan-pertanyaan dalam perjalanan sastra Indonesia, dulu-sekarang-dan akan datang.
Begitu pula pada Diskusi Sesi II di hari yang sama.
Mengambil tema “Kritik Sastra Indonesia Pascakolonial” dengan pembicara Dr. Syafrina Noorman, Yasraf Amir Piliang, Katrin Bandel, Zen Hae, dan moderator Willy Siswanto. Pertanyaan tentang identitas sastra Indonesia itu menukik pada persoalan 'keberadaan' kritik sastra yang kurang dari khazanah sastra Indonesia.
Yasraf Amir Piliang berpendapat, tugas kesusasteraan masa depan adalah membangun 'imajinasi' mandiri (self imagination), dengan meninggalkan 'imajinasi-imajinasi kolonial' atau imajinasi produksi 'sang lain', untuk mampu menghasilkan 'perbedaan' dan 'otentisitas', melalui sebuah sebuah proses 'menjadi diri sendiri' (becoming one-self). Dunia sastra diharapkan mampu membangun sebuah proses pertandaan (signification) yang melaluinya tanda-tanda budaya-budaya diperbedakan, makna-makna diproduksi, dan nilai-nilai dikembangkan. Sebuah proses 'resemiotasi' kebudayaan (cultural re-semiotizatian) melalui kekuatan sastra dapat diusulkan, dalam rangka pengkayaan dan penganekaragaman bentuk, makna dan nilai-nilai kebudayaan itu sendiri.
Pada hari ke dua, Sabtu (1 Agustus 2009), Diskusi Sesi III “Membaca Teks dan Gerakan Sastra Mutakhir: Mencari Subjek Pascakolonial” dengan pembicara Nenden Lilis Aisyah, Nurahayat Arif Permana, Zurmailis, Radhar Panca Dahana dan moderator Triyanto Triwikromo.
“Dalam perkembangan sastra kita pada era yang untuk sementara secara simplis saya sebut era reformasi ini, tema karya sastra cukup beragam. Namun, di antara tema-tema tersebut ada tema yang mendapat banyak sorotan. Tema yang dimaksud adalah tema mengenai femisme, dan tema seksualitas dan tubuh. Sorotan itu terjadi karena; pertama, radikal dan berani; kedua, karena dianggap ideologi barat,” ucap Nenden Lilis Aisyah.
Dikusi yang semustinya menarik—merujuk pada tema yang dihadirkan—terasa agak hambar. Selain pembicara yang kurang mampu menghidupkan diskusi, juga banyaknya kursi peserta yang kosong.
Sementara pada Diskusi Sesi IV, “Penerjemah Sastra Muktahir: Mencari Subjek Pascakolonial” dengan pembicara Anton Kurnia, Arif Bagus Prasetyo, John McGlym dan moderator Tia Setiadi.
Menurut Arif Bagus Prasetyo, penerjemahan adalah kegiatan yang amat kompleks. Bahasa itu sendiri sudah kompleks, tapi faktor-faktor yang terlibat dalam wacana manusia bahkan lebih kompleks. Tujuan terjemahan begitu beragam, dan pembaca karya terjemahan juga sangat beragam. Rasanya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa penerjemahan, mengutip pakar studi terjemahan, I. Richards, barangkali jenis peristiwa paling kompleks yang dihasilkan dalam evolusi jagad raya.
“Betapa memprihatikan kondisi karya terjemahan kita secara umum. Di antara sejumlah karya terjemahan yang bisa dibilang baik, amat banyak karya terjemahan yang buruk. Menurut Alfons yang pernah menjadi Ketua Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI), para penerjamalah yang paling bertanggung jawab atas kualitas karya terjemahan mereka. Namun, ia pun mengakui adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seorang penerjemah, seperti situasi sosial ekonomi, akses terhadap refrensi, serta penghargaan orang terhadap penerjemah dan hasil karyanya,” tutur Anton Kurnia.
Sementara John McGlynn dari Yayasan Lontar menilai tentang usaha penerjemahan Sastra Indonesia ke dalam bahasa Inggris, memiliki beberapa hambatan, yaitu kwalitas karya, ongkos penerbitan, sikap xenofobis, dan kurangnya visi pemerintah.
“Sebagaimana halnya dengan Indonesia yang mendapatkan hikmah dari pengetahuan mengenai kebudayaan lain, negara-negara lain dapat memperoleh manfaat dari ilmu yang berasal dari Indonesia—sebuah hal yang tidak akan terjadi kecuali orang Indonesia dapat mempromosikan diri secara aktif,” tukasnya.
Di mana Identitas Sastra Indonesia?
Selain Diskusi Sastra, TSI II 2009 yang dihadiri oleh pelaku sastra (Sastrawan dan Penikmat Sastra) dari berbagai wilayah yang ada di tanah air—yang setidaknya mewakili kantung sastra, baik muda mapun tua dalam proses kreatif—juga diisi dengan malam Apresiasi Sastra dan pertunjukan pembacaan karya sastra, peluncuran buku antologi sastra “Pedas Lada Pasir Kuarsa” (kumpulan puisi TSI II 2009) dan “Jalan Menikung ke Bukit Timah” (kumpulan cerpen TSI II 2009), Bazar Buku, dan Wisata Budaya.
Sudahkah identitas sastra Indonesia ditemukan? Terlalu naif jika dalam 4 hari untuk menagihnya. Peristiwa sastra di pulau Timah itu, barangkali bisa jadi 'modal' untuk menggali sastra Indonesia 'lebih' dan merangsang proses kreatif sastrawan. Di mana sastra Indonesia tidak sekedar selesai sebagai 'teks' semata dan tidak ada apa pun di luar 'teks' itu—hal ini bisa kita lihat dari penghargaan karya sastra yang ada, bahkan sekelas Nobel pun!--sebab omong kosong yang indah apabila sastra terbebas dari nilai di luar sastra itu sendiri. Sehingga ketika karya (sastra) selesai ditulis, pengarang cukup berleha-leha saja gara-gara salah kaprah memahami istilah, “pengarang sudah mati”.
Namun, bagaimana event sastra seperti Temu Sastrawan Indonesia itu tidak dijadikan sekedar sebuah pesta laiknya beberapa event sastra di Indonesia yang konon katanya bertaraf internasional. Bukan ajang 'bersolek' para sastrawan semata. Inilah tantangan bagi penyelenggara Temu Sastrawan Indonesia berikutnya 2010 di Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau.
Monday, August 17, 2009
Kredo Hidup
Kelahiran adalah ketika ruh menerima ajakan badan, menikmati kefanaan.
"Kau mewujudkan kegaibanku," kata ruh, kepada badan.
Kematian adalah ketika sampai saat ruh pulang, dan badan menolak ajakan.
"Aku telah mencemari kekudusanmu," kata badan, kepada ruh.
Kredo Merdeka
Bebas adalah ketika kita tidak lagi perlu bertanya-tanya, mencari-cari apakah makna kebebasan itu.
Merdeka adalah ketika kita tidak lagi berteriak "Merdeka!" hanya untuk meyakinkan bahwa kita telah benar-benar merdeka.
Saturday, August 15, 2009
Serampu Padam Lampu
KAU bagaikan kejutan hujan itu: seliar terbiar di luar
Aku dikuasai dinginmu, tersiram sepi di samar kamar
Nyaris saja, terselulur lumut si selimut batu, tadi,
di sumur umur. Sempat kau menyerampu padam lampu?
Kredo Hidup
Kelahiran adalah ketika ruh menerima
ajakan badan, menikmati kefanaan.
"Kau mewujudkan kegaibanku," kata ruh,
kepada badan.
Kematian adalah ketika sampai saat ruh
pulang, dan badan menolak ajakan.
"Aku telah mencemari kekudusanmu," kata
badan, kepada ruh.
Friday, August 14, 2009
Poem
Ngai Oi Ngi
waktu yang singkat
menyusun ingatan yang panjang, mei lan
di belinyu, di belinyu
kita bertemu
ruko-ruko tutup pada jam 4 petang
dikepung bekas lubang-lubang tambang
yang ditinggalkan
aku menggenggam tanganmu lebih dalam
--tangan yang datang dari negeri hutan terbakar--
di benteng bongkap, pha kak liang
pantai penyusuk, atau di bawah bulan
ketika listrik padam
pada jam 9 malam
tetapi sepanjang jalan depati amir
angin mengembalikan tangan kita
jadi milik kita masing-masing
agar bisa menangkap senja
bangunan-bangunan tua
dari masa gemilang timah
hingga kesedihan
orang-orang hakka
dalam pembakaran taiseja
agar bisa merasakan
suara mereka yang hidup dan tak bisa pulang
lalu membangun kampung dalam dirinya
jauh lebih sunyi, jauh lebih sunyi
daripada sihir puisi
igauan pelayaran
yang tak pernah menyentuh lautan
Belinyu-Yogyakarta, Agustus 2009
Poem
Ngai Oi Ngi
waktu yang singkat
menyusun ingatan yang panjang, mei lan
di belinyu, di belinyu
kita bertemu
ruko-ruko tutup pada jam 4 petang
dikepung bekas lubang-lubang tambang
yang ditinggalkan
aku menggenggam tanganmu lebih dalam
--tangan yang datang dari negeri hutan terbakar--
di benteng bongkap, pha kak liang
pantai penyusuk, atau di bawah bulan
ketika listrik padam
pada jam 9 malam
tetapi sepanjang jalan depati amir
angin mengembalikan tangan kita
jadi milik kita masing-masing
agar bisa menangkap senja
bangunan-bangunan tua
dari masa gemilang timah
hingga kesedihan
orang-orang hakka
dalam pembakaran taiseja
agar bisa merasakan
suara mereka yang hidup dan tak bisa pulang
lalu membangun kampung dalam dirinya
jauh lebih sunyi, jauh lebih sunyi
daripada sihir puisi
igauan pelayaran
yang tak pernah menyentuh lautan
Belinyu-Yogyakarta, Agustus 2009
Thursday, August 13, 2009
[KOLOM] Gairah Rendra
Oleh Hasan Aspahani
Pemimpin Redaksi Batam Pos
KAMIS, 6 Agustus 2009, Wahyu Sulaiman Rendra meninggal. Usia berhenti di angka 74. Ia tak akan pernah lagi berada di mimbar-mimbar resitasi puisi, di panggung pementasan drama, atau di podium orasi. Tapi, ia meninggalkan banyak hal berharga bagi kita, orang yang hidup sesudah dia, juga bagi negeri ini.
KAMIS, 6 Agustus 2009, Wahyu Sulaiman Rendra meninggal. Usia berhenti di angka 74. Ia tak akan pernah lagi berada di mimbar-mimbar resitasi puisi, di panggung pementasan drama, atau di podium orasi. Tapi, ia meninggalkan banyak hal berharga bagi kita, orang yang hidup sesudah dia, juga bagi negeri ini.
Selain sajak-sajak yang akan abadi menginspirasi orang dari zaman ke zaman, ia juga meninggalkan sejumlah artikel hasil pemikiran dan permenungannya. Tulisan-tulisan itu sama bernilainnya, sama pentingnya.
Meski tak terlalu mengerti, dulu, pada usia yang sangat dini, saya adalah orang yang tersemangati oleh apa yang dia sebut sebagai "daya hidup". Artikel tentang hal itu - sekarang susah sekali anak muda kita mendapatkan tulisan dengan daya gugah serupa itu - ditulisnya di sebuah majalah remaja di tahun 1986.
Bayangkan, seorang penyair besar menulis di sebuah majalah remaja. Ini adalah bagian dari serangkaian artikel bermuatan motivasi sangat tinggi, menggugah, dan bak tenaga banjir bah, ia mendobrak kesadaran. Pokoknya - semoga saya tidak berlebihan - ini tulisan yang bikin saya berani dan kreatif!
Saya bertanya pada Arswendo Atmowiloto tentang riwayat serial naskah Rendra itu. Sebenarnya, kata Wendo yang saat itu mengomandani majalah Hai di mana artikel itu terbit, artikel itu semacam "kecelakaan".
"Kami minta Rendra menulis tentang bermain drama," kata Wendo pada saya. "Tapi, Rendra ya begitu. Dia nulis macam-macam, melenceng dari yang diminta, dan ternyata bagus. Jadi dibiarkan saja," katanya.
Redaksi Hai juga tak menagih tulisan lagi ketika tiba-tiba Rendra saja berhenti menulis, tak menyelesaikan serial tulisannya sesuai kesepakatan. "Padahal honornya dibayar di depan, dan jauh lebih mahal dari tarif honor majalah Hai," kenang Wendo.
Apa yang ditulis Rendra? Mari kita baca - artikel itu kelak dibukukan bersama sejumlah tulisan lain dibawah judul "Rendra Memberi Makna pada Hidup yang Fana" - bagian pertama tentang "Kepribadian".
Supaya mudah, saya butir-butirkan apa yang dia tulis. Dan sebisanya, saya uraikan butir-butir itu.
1. Manusia adalah gabungan dari keterbatasan dan kemungkinan. Ada batas untuk cita-cita dan perencanaan manusia. Ada batas kenyataan alam yang harus diperhatikan.
Saya perlu waktu lama bagi saya untuk menelaah apa yang ia tulis itu. Tapi betapa benarnya, bukan? Kita memang dibatasi, tapi di balik keterbatasan itu ada kemungkinan yang harus kita cari, kita temukan. Jadi, pesan moralnya, jangan mengalah pada keterbatasan itu.
2. Ada pula watak-watak buruk yang membatasi kemampuan diri, yaitu kemalasan, kebodohan, ketakutan, ketidakjujuran, dan sebagainya.
Moral, Tuan Rendra. Moral. Itu yang engkau maksudkan bukan? Ya, etos kerja juga, keberanian juga, integritas juga, kecerdikan juga. Saya kira, kalau Rendra terjun ke dunia bisnis, dia akan jadi pebisnis yang hebat. Kalau dia terjun ke politik, dia akan jadi presiden. Saya kira begitu.
3. Pribadi yang mekanis yang serupa mesin, tidak pernah menyadari kemungkinan dan keterbatasan dan serupa itu. ia sudah disetel dan hidup berdasarkan setelannya.
Fleksibilitas. Kelenturan. Jangan jadi manusia yang kaku. Jangan mau disetel oleh keterbatasan kita. Jangan jadi mesin yang bekerja mekanistik. Manusia bukan mesin. Manusia mesin mungkin bekerja efektif untuk satu hal saja, tetapi dia akan tak berdaya ketika menghadapi masalah di luar satu hal itu. Jadi, jangan terpenjara pada keterbatasan dan karena itu jadi tak mampu menciptakan kemungkinan-kemungkian yang lebih baik.
4. Pribadi-pribadi yang kreatif justru memperhatikan keterbatasan dan kemungkinan yang ada di dalam dan di luar dirinya. Berkat kemauan dan kemampuannya, mereka berusaha agar kemungkinan itu bisa ada. Namun, sebelum itu keterbatasan-keterbatasan di dalam alam dan di dalam hidup ini perlu lebih dahulu disadari dan dipelajari.
Inti dari daya hidup itu adalah kreativitas. Kita tidak bisa kreatif, kalau kita tidak punya daya cipta. Kita tidak punya daya cipta kalau kita tidak tahu apa yang ada dan yang tidak ada di sekitar kita. Mencipta, bukankah itu mengadakan sesuatu yang semula tidak ada? Kata Rendra, "hanya dengan cara serupa itu ia mampu merencanakan kemajuan yang sungguh bisa dilaksanakan karena rencananya memang berdasarkan kenyataan."
5. Pribadi yang kreatif selalu merasa perlu untuk menilik dan mengoreksi diri. Ia perlu menciptakan suasana terbuka di dalam jiwanya sehingga ia bisa melakukan koreksi diri.
Nah, jika ajakan untuk kreatif adalah ajakan untuk berlari, maka Rendra pun mengajarkan bahwa kita harus sesekali berhenti, juga memperlamat laju lari itu. Ia mengajarkan untuk tidak tinggi hati. Kita harus menggapai langit, tapi tetap harus berpijak di bumi.
6. Manusia itu penuh daya yang kompleks dan sukar diduga. Apabila dilatih dengan baik, otot-ototnya, pancaindranya, syaraf-syarafnya, intuisinya, perasaannya, dan pikirannya akan merupakan sumber kemungkinan yang sangat besar.
Rendra percaya pada kemuliaan kerja. Ia suka pada remaja yang meskipun kurang sekolahan tetapi melihat seonggok jagung di kamar sebagai sebuah kemungkinan. Ia suka pada pemuda yang otak dan tangannnya siap bekerja. Sebagaimana dalam "Sajak Seonggok Jagung", pemuda itu ia bandingkan dengan pemuda lain yang tamat SMA tetapi tidak terlatih dengan metode. Ia benci pemuda yang pandangannya mencontek dari teks buku, bukan dari kehidupan.
7. Gairah usaha sangat menentukan dalam mengolah keterbatasan menjadi kemungkinan.
Gairah. Semangat. Ia tunjukkan itu pada bidangnya. Ia pendobrak teater modern di Indonesia. Ia mendirikan sebuah teater dengan metode latihan unik yang belum pernah ada sebelumnya, dan melahirkan seniman-seniman yang handal yang menjulang di jagad seni negeri ini. Bisakah itu semua dilakukan dengan semangat dan gairah yang setengah-setengah? Tidak!
"Saya tidak sedih, Rendra meninggal," kata Sutardji Calzoum Bachri. Kenapa? Karena dia tidak pernah meninggalkan kita, karena dia meninggalkan karya-karyanya. Karya-karyanya abadi untuk kita.
Maka, saya kira, yang menyedihkan adalah kalau kita tidak mengambil pelajaran dari karya-karya yang dia tinggalkan, buku-buku sajak-sajaknya, rekaman resitalnya, naskah-naskah teaternya, dan buah-buah pemikirannya. Kalau kita tidak melakukan itu, kita yang maharugi, dan saya kira di alam sana, Rendra akan bersedih karenanya.***
Wednesday, August 12, 2009
Perakit Bunga
: Ibrohim
TIDAK ada toko bom di hotel itu,
hanya sebuah gerai menjual bunga,
kau bekerja di sana. Merakit bunga.
Ada hari ketika kau meledakkan bunga.
Di mana kau merangkainya? Di sebuah
kamar pengantin dipilih dan dipesan,
di hotel itu? Hmm, persandingan tanpa
undangan. Aduh, kau tahu apa yang
kau telah siar-siarkan itu (lewat
bunga yang membunuhmu), yang telah
amat kau sia-siakan? Yang kau tanam,
seharusnya bisa juga tumbuh menjadi
pohon bunga, teduh cabang-cabangnya,
dan jatuh sendiri nanti bunganya,
kelak di harum sebuah hari, bukan?
Tak ada panser singgah di hotel itu,
hanya sebuah pikap terbuka, kau
mengirim kotak-kotak bunga ke sana.
Kau mengirim dirimu ke taman bunga,
yang mungkin akan salah alamatnya!
Sunday, August 9, 2009
Catatan Perjalanan
Ke Belinyu Saja, Melihat Kota Tua Timah
Sementara saya menampik tawaran mengunjungi Pantai Tanjung Bunga, Hutan Wisata TuaTunu, Kuburan Cina Sentosa, Katedral ST. Yosef, Kuburan Akek Bandang, Museum Timah Indonesia, Rumah Eks Residen, Perigi Pasem, Tugu Kemerdekaan, Kerhof, yang ditawarkan oleh dinas Pariwisata Bangka-Belitung lewat buklet bagi peserta Temu Sastrawan Indonesia II yang hendak melancong.
Bukan karena tempat itu tidak menarik, tapi saya ingin sesuatu yang beda. Saya ingin mengunjungi objek wisata yang tidak terpromosikan. Berdasarkan pengalaman saya sebelumnya, tempat seperti itu kadang memiliki pesona yang tersembunyi.
Gayung bersambut! Kebetulan Raudal Tanjung Banua, Nurwahida Idris, Tsabit, Kedung Darma Romansah, (Yogyakarta), Nur Zen Hae beserta anak istrinya (Jakarta), Risa Syukria (Siak), dan Dahlia (Palembang), hendak bertandang ke rumah Sunlie Thomas Alexander di Belinyu.
Bersama rombongan peserta Temu Sastrawan Indonesia II di Pangkalpinang (30 Juli-2 Agustus 2009) yang masih belum bergegas pulang ke daerah masing-masing meski event tahunan itu sudah usai, saya menumpangi bus Damri yang disediakan oleh dinas Pariwisata negeri Timah itu.
Selama perjalanan dari Pangkalpinang ke Belinyu, saya pergunakan untuk melihat daerah yang dilintasi dari kaca bus yang melaju dalam angin petang. Beberapa kali saya tertegun, setiap kali melihat bekas-bekas lubang tambang timah yang ditinggalkan dan terbengkalai. Dan pohon-pohon yang tidak seramai laiknya di tepi Lintas Sumatera, berjajar rapat menatap bus yang melintas.
Duh, kegersangan yang menciptakan kesedihan. Tapi saya musti melihatnya. Melihatnya sebagai pelancong yang hanya bisa bertanya “kenapa?” tanpa menemukan jawaban yang memuaskan. Sebab tidak ada guide dalam rombongan kami selama perjalanan di bus itu. Diam-diam, kami seperti bersepakat menjadi guide bagi diri kami sendiri. Seperti sengaja menciptakan pertanyaan-pertanyaan bagi diri kami sendiri dan dijawab oleh diri kami sendiri.
Tak terasa lebih kurang 3 jam, bus itu mengantarkan kami ke kota kecamatan Belinyu. Sebuah kota tua yang didirikan karena pertambangan timah.
Kami disambut deretan bangunan-bangunan tua dan ruko-ruko yang sebagian besar tutup. Padahal baru jam 5 sore. Lagi-lagi saya didera pertanyaan “kenapa?”
Karena tidak tahan, saya pun bertanya kepada Sunlie, “Kenapa ruko-ruko di sini tutup?”
“Di sini orang-orang berdagang cuma sampai jam 4 petang,” jawab Sunlie.
Lalu ia mengajak saya masuk ke rumahnya, menyusul yang lain.
Di depan pintu, saya disambut oleh Mama Sunlie yang berumur sekitar 60-an dan ramah. Ia Menyapa saya dalam bahasa Cina Hakka. Saya cuma bisa memberi senyum, lantaran tidak faham bahasa Hakka itu.
“Mama saya tidak bisa ngomong dengan bahasa Indonesia,” ucap Sunlie.
Di Belinyu sekitar 30 persen penduduknya adalah Cina Hakka.
Dalam sejarah Cina perantauan (Overseas Chinese) ke Asia Tenggara, setidaknya dikenal 5 kelompok besar yang datang dan menetap, yaitu Hokkian,Hakka, Tiochiu atau Hoklo, Kanton, dan Hailam.Kelompok Hokkian dan Tiochiu dikenal sebagai kelompok pedagang, Kanton sebagai kelompok pengrajin dan tukang kayu.
Hakka sebagai pekerja tambang dan perkebunan. Dalam sejarah, Hakka adalah kelompok terakhir yang datang ke Indonesia . Mereka datang berombongan untuk dipekerjakan sebagai kuli tambang dan perkebunan.
Kedatangan Hakka pertama adalah ke Mandor dan Montrado, pertambangan emas yang dikonsesi oleh Sultan Mempawah dan Sambas, Sekitar awal tahun 1700, mereka didatangkan dalam jumlah besar melalui Serawak.
Ketika tambang timah di Bangka di buka sekitar pertengahan tahun 1700, yang disusul kemudian di Belitung, beratus-ratus orang Hakka dikapalkan ke Bangka. Dan terus berlanjut hingga pertengahan tahun 1800. Rata-rata didatangkan dari Meixien. Mereka datang tanpa membawa istri.
Ketika kontrak habis hanya ada dua pilihan, kembali ke Cina atau menetap di sekitar lokasi tambang. Bagi mereka yang tidak pulang membuka permukiman di Bangka, seperti di Belinyu.
Putusan untuk menetap diikuti dengan mengambil wanita setempat sebagai istri.
Arsitektur permukiman mereka telah berbaur dengan budaya setempat. Namun yang masih terlihat menonjol adalah banyaknya tapekong (tempat pemujaan besar kecil dalam permukiman itu).
Berbagai perayaan besar dalam tradisi Cina masih mereka lakukan. Sembahyang Imlek masih dirayakan dengan ketat, seperti pantangan menyapu pada hari Imlek, saling memberi Angpau, perayaan Cengbeng atau Cingming (perayaan bersih kubur leluhur). Begitu pula dengan Cioko atau sembahyang rebut, masih dilakukan.
Yang tak kalah menarik, di Belinyu memiliki tradisi mengadakan pembakaran Taiseja. Dalam perayaan itu juga disertakan berbagai replika alat transportasi seperi kapal laut, kapal terbang, dan sebagainya. Menurut Sunlie, itu disediakan bagi arwah-arwah orang Cina yang hendak pulang ke negeri leluhur.
Sayangnya, saya tidak datang pada saat perayaan itu berlangsung.
Namun, jalan-jalan melewati rumah-rumah kuno beraksitektur campuran Melayu-Cina-Belanda, pedagang buah-buahan, martabak Bangka, Sate Madura, Warung Pecel Lele, Bakso Solo, Ampera Padang, Otak-otak Bakar, Mpek-mpek, di bawah cahaya bulan malam itu menciptakan nuansa eksotis. Apalagi kelengangan memberikan kedamaian tersendiri. Jauh dari suasana kota metropolis yang hiruk-pikuk.
Kapitan Bongkap, Benteng Kutopanji, Kelenteng Liang San Phak
Merasakan malam pertama di kota Belinyu dengan listrik yang mati hingga subuh. Karena listrik bermasalah. Sebagian jaringan Listrik dilayani PT Timah karena PLN kekurangan jaringan. PLTU Mantung dekat pelabuhan Belinyu, yang pernah dibilang terbesar di Asia Tenggara, sudah lama tidak berfungsi. Pun PLTD di Baturusa, setali tiga uang. Sama saja. PT Timah akhirnya menjadi pemasok listrik tanpa meteran, dengan sistem borongan. Tapi layanannya masih mengecewakan, listriknya sering padam.
“Bangun! Lihat ke bawah,” ujar Raudal membangunkan saya dari tidur.
Dari beranda lantai atas rumah Sunlie, saya melihat ke bawah. Ada bus-bus umum ngetem di depan rumah Sunlie. Bus-bus itu sangat antik. Bodinya terbuat dari kayu yang dilapisi seng. Ada tangga menuju bagasi berpagar besi di atap bus itu. Saya jadi ingat waktu kecil dulu, bus keluaran tahun 1970-an macam itu pernah saya tumpangi bersama Papa dari Padang ke Bukittingi pertengahan tahun 1980-an.
“Sungguh kota tua yang masih menyimpan masa lalunya,” bisik saya pada pagi yang mulai menggeliat bersama pedagang-pedagang yang membuka pintu tokonya.
Pukul 10 pagi, saya beserta rombongan melancong ke luar kota dengan mobil rental kijang Inova. Berdesakan memang, karena mobil itu dinaiki saya, Raudal Tanjung Banua, Nurwahida Idris, Tsabit, Kedung Dharma Romansah, Nur Zen Hae beserta anak istrinya, Risa Syukria, Dahlia, Sunlie Thomas Alexander dan tentu saja Pak sopir. Tapi suasana riang bikin yang sempit jadi lapang.
Menempuh jarak 2 kilometer dari pusat kota Belinyu, sampailah kami di Benteng Kutopanji atau Benteng Bongkap, terletak di kampung Kusam.
Kekokohan sisa-sisa bangunan Benteng berwaran hitam keabuan—terbuat dari tanah liat yang dibakar—yang dibangun sekitar 1700 oleh Kapitan Bong atau Bong Khiung Fu , membuat saya terpesona. Meski yang saya jumpai sekarang adalah sisa-sisa dan kisah tentang Kapitan Bongkap, saudagar Cina yang kaya raya dan seorang pelarian politik.
Kami masuk ke dalam benteng, menemukan dua makam dengan arsitektur Cina di bagian paling belakang Benteng itu.
Yang terbesar adalah makam Kapitan Bong bertahun 1700 dan dipugar pada tahun 1973, di belakangnya di atas tebing adalah makam pengawalnya. Namun itu adalah replika makam Kapitan Bong, tapi tetap dihormati oleh masyarakat setempat. Karena sebenarnya, Kapitan itu meninggal di Malaysia dan Benteng Kutopanji jatuh ke tangan perompak Moro, Filipina.
Kemudian kami singgah ke Kelenteng Liang San Phak yang berdampingan dengan Benteng Kutopanji di sisi barat.
Kelenteng Liang San Phak, sebenarnya merupakan bagian dari Benteng Kutopanji yang juga didirikan oleh Kapitan Bong.
Aroma Hio menyambut kami. Nur Zen Hae, Risa Syukria, Kedung Darma Romansah, dan Dahlia, mencoba bergantian mengadu peruntungan dan ramalan nasib dengan membakar Hio di depan patung Thai Pak Kong (Paman Besar) bernama Liang San Phak dan patung istrinya, yang dibawa langsung oleh Kapitan Bong dari negeri leluhurnya. Patung ini pada tanggal 15 bulan ketujuh penanggalan Cina, diarak mengelilingi kota Belinyu sebagai prosesi sembahyang rebut.
“Ini Klenteng Dewa Bumi atau Tapekong. Menurut agama Konghucu, Klenteng Tapekong ini untuk tempat bersembahyang dan meminta agar rezeki banyak dan keselamatan,” ujar Fujianto alias Afu (35), salah seorang pengurus Klenteng.
Saya ingin bertanya lebih banyak lagi pada Afu yang ramah itu. Tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, perjalanan musti dilanjutkan.
Pha Kak Liang
Setelah melewati jalan tanah berdebu, dan sesekali bertemu pula dengan bekas tambang timah yang ditinggalkan, sampailah kami di gerbang utama Pha Kak Liang yang bernuansa Cina. Makin ke dalam, arsitektur Cina itu makin terasa. Seperti demarga, rumah peristirahatan, gazebo, semuanya berornamen Cina.
Pha Kak Liang adalah sebuah objek wisata tirta yang dibangun di atas bekas tambang timah (kolong). Terletak 10 Kilometer dari kota Belinyu.
Keheningan dan kedamaian begitu terasa di tepi telaga seluas 3,5 hektar yang ditumbuhi pohon cemara dan akasia. Pemiliknya tiga orang etnis Cina bersaudara, dan menjadikannya sebagai villa peristirahatan, yang tetap terbuka untuk umum.
Sayangnya, kurang terawatnya Pha Kak Liang membuat objek wisata degan telaga berisi ribuan ikan emas yang hidup bebas itu tampak sedikit suram. Tapi bagi pecinta suasana sunyi, Pha Kak Liang memberikan itu. Dan semakin lama akan makin terasa.
Namun, lagi-lagi perjalanan musti dilanjutkan.
Pantai Penyusuk
“Lihat pohon-pohon yang memeluk batu itu!” ucap Raudal.
Kalimat Raudal yang puitis itu seperti memberi tahu bahwa kami telah memasuki gerbang pantai Penyusuk. Ya, di kiri-kanan jalan memasuki area pantai tampak beberapa batu besar yang di sekilingnya di tumbuhi pohon-pohon.
Hamparan pantai yang landai dan ditumbuhi batu-batu besar menyambut kami. Beberapa perahu nelayan tertambat. Ombaknya tenang karena di depannya ada pulau cukup besar yang menjadi tameng. Sedang pulau kecil di sampingnya, berdiri menara suar yang tampak sebesar pohon nyiur melambai dari tempat saya berdiri.
Amboi! Negeri rayuan pulau kelapa, alangkah eloknya.
Saya tidak sabaran ingin menceburkan diri. Mandi-mandi di laut jadi kanak-kanak ria kembali. Hilang sejenak segan pada usia.
Namun Risa Syukria meminta saya untuk menemani dia mengambil air wudhu. Inilah perkaranya, ternyata kamar mandi umum dikunci. Penjaganya entah kemana.
Memang pantai Penyusuk sepi, jauh dari pedagang yang mata duitan. Akhirnya, kami menemukan berbungkus-bungkus air minum tergeletak ditinggalkan pemiliknya di atas sebuah batu besar.
Jadilah Risa sholat dan saya pun mandi menceburkan diri ke laut menyusul yang lain, yang telah dulu bermain dengan air garam yang jinak itu. Tak lama berselang, Risa pun menyusul.
Cuma Kedung Darma Romansah dan Pak sopir yang tidak mau membasahi tubuhnya dengan air laut di pantai yang tenang itu. Entah kenapa.
Setelah puas mandi-mandi. Main pasir pantai yang putih. Duduk-duduk dari satu batu ke lain batu. Rombongan sastrawan itu memutuskan untuk pulang.
Matahari sudah mulai mendekati ubun-ubun laut, beberapa jam lagi bakal angslup. Cuaca cerah. Tentu saja sunset akan terlihat terlihat sempurna di pantai barat ini. Namun apa hendak dikata, pertemuan matahari dan laut yang menciptakan cahaya emas itu, tak bisa saya saksikan.
Kami pun pulang dengan tubuh yang belum dibilas dari air laut karena penjaga kamar mandi umum itu tidak juga datang.
Sesampai di jalan Depati Amir, saya dan Risa Syukria yang juga reporter TV Siak, memutuskan turun dari mobil. Kami ingin berjalan kaki berdua menuju rumah Sunlie di jalan Sriwijaya yang jaraknya sekitar 500 meter dari tempat kami turun. Sedang yang lain terus pulang dengan mobil.
Kami turun dari mobil itu bukan karena ngambek, tapi ingin melihat lebih dekat rumah-rumah arsitektur Belanda yang dihuni pegawai timah di bawah gelimang cahaya senja.
Ya, sepanjang jalan Depati Amir itu berjajar bangunan-bangunan lama. Sayang sebagian sudah tidak terawat lagi. Padahal bangunan-bangunan itu merupakan jejak langkah dari perjalanan kota timah itu.
Menurut Ibrahim (52) salah seorang karyawan pertambangan timah yang kami temui di salah rumah kuno itu, dulunya rumah-rumah di kawasan jalan Depati Amir itu adalah kawasan elit yang ditempati oleh pegawai teras atas pertambangan timah. Dibangun pada tahun 1928.
Namun sejak menipisnya cadangan timah di Belinyu, rumah-rumah itu dihuni campur aduk antara karyawan biasa dan pegawai menengah. Bahkan sebagian rumah tidak dihuni lagi dalam kondisi yang mengenaskan, pintu dan jendela yang copot, serta dindingnya kumuh penuh coretan.
“Kota yang aneh. Tidak seperti kota-kota lain yang pernah saya datangi. Selama di sini, belum pernah saya lihat ada ABG nongkrong bersama menghabiskan petang. Bagaimana ya orang-orang hidup dalam kelengangan ini?” ucap Risa, dara rancak asal Minang ini, di jalan menuju ke rumah Sunlie—selepas jalan Depati Amir.
“Kota ini membuat Ngai Oi Ngi!” ujar saya memakai sekerat bahasa Hakka yang saya pelajari dari Sunlie.
“Apa itu Ngai Oi Ngi?” tanya Risa.
“Aku Mencintaimu!”
Catatan Perjalanan
Ke Belinyu Saja, Melihat Kota Tua Timah
Sementara saya menampik tawaran mengunjungi Pantai Tanjung Bunga, Hutan Wisata TuaTunu, Kuburan Cina Sentosa, Katedral ST. Yosef, Kuburan Akek Bandang, Museum Timah Indonesia, Rumah Eks Residen, Perigi Pasem, Tugu Kemerdekaan, Kerhof, yang ditawarkan oleh dinas Pariwisata Bangka-Belitung lewat buklet bagi peserta Temu Sastrawan Indonesia II yang hendak melancong.
Bukan karena tempat itu tidak menarik, tapi saya ingin sesuatu yang beda. Saya ingin mengunjungi objek wisata yang tidak terpromosikan. Berdasarkan pengalaman saya sebelumnya, tempat seperti itu kadang memiliki pesona yang tersembunyi.
Gayung bersambut! Kebetulan Raudal Tanjung Banua, Nurwahida Idris, Tsabit, Kedung Darma Romansah, (Yogyakarta), Nur Zen Hae beserta anak istrinya (Jakarta), Risa Syukria (Siak), dan Dahlia (Palembang), hendak bertandang ke rumah Sunlie Thomas Alexander di Belinyu.
Bersama rombongan peserta Temu Sastrawan Indonesia II di Pangkalpinang (30 Juli-2 Agustus 2009) yang masih belum bergegas pulang ke daerah masing-masing meski event tahunan itu sudah usai, saya menumpangi bus Damri yang disediakan oleh dinas Pariwisata negeri Timah itu.
Selama perjalanan dari Pangkalpinang ke Belinyu, saya pergunakan untuk melihat daerah yang dilintasi dari kaca bus yang melaju dalam angin petang. Beberapa kali saya tertegun, setiap kali melihat bekas-bekas lubang tambang timah yang ditinggalkan dan terbengkalai. Dan pohon-pohon yang tidak seramai laiknya di tepi Lintas Sumatera, berjajar rapat menatap bus yang melintas.
Duh, kegersangan yang menciptakan kesedihan. Tapi saya musti melihatnya. Melihatnya sebagai pelancong yang hanya bisa bertanya “kenapa?” tanpa menemukan jawaban yang memuaskan. Sebab tidak ada guide dalam rombongan kami selama perjalanan di bus itu. Diam-diam, kami seperti bersepakat menjadi guide bagi diri kami sendiri. Seperti sengaja menciptakan pertanyaan-pertanyaan bagi diri kami sendiri dan dijawab oleh diri kami sendiri.
Tak terasa lebih kurang 3 jam, bus itu mengantarkan kami ke kota kecamatan Belinyu. Sebuah kota tua yang didirikan karena pertambangan timah.
Kami disambut deretan bangunan-bangunan tua dan ruko-ruko yang sebagian besar tutup. Padahal baru jam 5 sore. Lagi-lagi saya didera pertanyaan “kenapa?”
Karena tidak tahan, saya pun bertanya kepada Sunlie, “Kenapa ruko-ruko di sini tutup?”
“Di sini orang-orang berdagang cuma sampai jam 4 petang,” jawab Sunlie.
Lalu ia mengajak saya masuk ke rumahnya, menyusul yang lain.
Di depan pintu, saya disambut oleh Mama Sunlie yang berumur sekitar 60-an dan ramah. Ia Menyapa saya dalam bahasa Cina Hakka. Saya cuma bisa memberi senyum, lantaran tidak faham bahasa Hakka itu.
“Mama saya tidak bisa ngomong dengan bahasa Indonesia,” ucap Sunlie.
Di Belinyu sekitar 30 persen penduduknya adalah Cina Hakka.
Dalam sejarah Cina perantauan (Overseas Chinese) ke Asia Tenggara, setidaknya dikenal 5 kelompok besar yang datang dan menetap, yaitu Hokkian,Hakka, Tiochiu atau Hoklo, Kanton, dan Hailam.Kelompok Hokkian dan Tiochiu dikenal sebagai kelompok pedagang, Kanton sebagai kelompok pengrajin dan tukang kayu.
Hakka sebagai pekerja tambang dan perkebunan. Dalam sejarah, Hakka adalah kelompok terakhir yang datang ke Indonesia . Mereka datang berombongan untuk dipekerjakan sebagai kuli tambang dan perkebunan.
Kedatangan Hakka pertama adalah ke Mandor dan Montrado, pertambangan emas yang dikonsesi oleh Sultan Mempawah dan Sambas, Sekitar awal tahun 1700, mereka didatangkan dalam jumlah besar melalui Serawak.
Ketika tambang timah di Bangka di buka sekitar pertengahan tahun 1700, yang disusul kemudian di Belitung, beratus-ratus orang Hakka dikapalkan ke Bangka. Dan terus berlanjut hingga pertengahan tahun 1800. Rata-rata didatangkan dari Meixien. Mereka datang tanpa membawa istri.
Ketika kontrak habis hanya ada dua pilihan, kembali ke Cina atau menetap di sekitar lokasi tambang. Bagi mereka yang tidak pulang membuka permukiman di Bangka, seperti di Belinyu.
Putusan untuk menetap diikuti dengan mengambil wanita setempat sebagai istri.
Arsitektur permukiman mereka telah berbaur dengan budaya setempat. Namun yang masih terlihat menonjol adalah banyaknya tapekong (tempat pemujaan besar kecil dalam permukiman itu).
Berbagai perayaan besar dalam tradisi Cina masih mereka lakukan. Sembahyang Imlek masih dirayakan dengan ketat, seperti pantangan menyapu pada hari Imlek, saling memberi Angpau, perayaan Cengbeng atau Cingming (perayaan bersih kubur leluhur). Begitu pula dengan Cioko atau sembahyang rebut, masih dilakukan.
Yang tak kalah menarik, di Belinyu memiliki tradisi mengadakan pembakaran Taiseja. Dalam perayaan itu juga disertakan berbagai replika alat transportasi seperi kapal laut, kapal terbang, dan sebagainya. Menurut Sunlie, itu disediakan bagi arwah-arwah orang Cina yang hendak pulang ke negeri leluhur.
Sayangnya, saya tidak datang pada saat perayaan itu berlangsung.
Namun, jalan-jalan melewati rumah-rumah kuno beraksitektur campuran Melayu-Cina-Belanda, pedagang buah-buahan, martabak Bangka, Sate Madura, Warung Pecel Lele, Bakso Solo, Ampera Padang, Otak-otak Bakar, Mpek-mpek, di bawah cahaya bulan malam itu menciptakan nuansa eksotis. Apalagi kelengangan memberikan kedamaian tersendiri. Jauh dari suasana kota metropolis yang hiruk-pikuk.
Kapitan Bongkap, Benteng Kutopanji, Kelenteng Liang San Phak
Merasakan malam pertama di kota Belinyu dengan listrik yang mati hingga subuh. Karena listrik bermasalah. Sebagian jaringan Listrik dilayani PT Timah karena PLN kekurangan jaringan. PLTU Mantung dekat pelabuhan Belinyu, yang pernah dibilang terbesar di Asia Tenggara, sudah lama tidak berfungsi. Pun PLTD di Baturusa, setali tiga uang. Sama saja. PT Timah akhirnya menjadi pemasok listrik tanpa meteran, dengan sistem borongan. Tapi layanannya masih mengecewakan, listriknya sering padam.
“Bangun! Lihat ke bawah,” ujar Raudal membangunkan saya dari tidur.
Dari beranda lantai atas rumah Sunlie, saya melihat ke bawah. Ada bus-bus umum ngetem di depan rumah Sunlie. Bus-bus itu sangat antik. Bodinya terbuat dari kayu yang dilapisi seng. Ada tangga menuju bagasi berpagar besi di atap bus itu. Saya jadi ingat waktu kecil dulu, bus keluaran tahun 1970-an macam itu pernah saya tumpangi bersama Papa dari Padang ke Bukittingi pertengahan tahun 1980-an.
“Sungguh kota tua yang masih menyimpan masa lalunya,” bisik saya pada pagi yang mulai menggeliat bersama pedagang-pedagang yang membuka pintu tokonya.
Pukul 10 pagi, saya beserta rombongan melancong ke luar kota dengan mobil rental kijang Inova. Berdesakan memang, karena mobil itu dinaiki saya, Raudal Tanjung Banua, Nurwahida Idris, Tsabit, Kedung Dharma Romansah, Nur Zen Hae beserta anak istrinya, Risa Syukria, Dahlia, Sunlie Thomas Alexander dan tentu saja Pak sopir. Tapi suasana riang bikin yang sempit jadi lapang.
Menempuh jarak 2 kilometer dari pusat kota Belinyu, sampailah kami di Benteng Kutopanji atau Benteng Bongkap, terletak di kampung Kusam.
Kekokohan sisa-sisa bangunan Benteng berwaran hitam keabuan—terbuat dari tanah liat yang dibakar—yang dibangun sekitar 1700 oleh Kapitan Bong atau Bong Khiung Fu , membuat saya terpesona. Meski yang saya jumpai sekarang adalah sisa-sisa dan kisah tentang Kapitan Bongkap, saudagar Cina yang kaya raya dan seorang pelarian politik.
Kami masuk ke dalam benteng, menemukan dua makam dengan arsitektur Cina di bagian paling belakang Benteng itu.
Yang terbesar adalah makam Kapitan Bong bertahun 1700 dan dipugar pada tahun 1973, di belakangnya di atas tebing adalah makam pengawalnya. Namun itu adalah replika makam Kapitan Bong, tapi tetap dihormati oleh masyarakat setempat. Karena sebenarnya, Kapitan itu meninggal di Malaysia dan Benteng Kutopanji jatuh ke tangan perompak Moro, Filipina.
Kemudian kami singgah ke Kelenteng Liang San Phak yang berdampingan dengan Benteng Kutopanji di sisi barat.
Kelenteng Liang San Phak, sebenarnya merupakan bagian dari Benteng Kutopanji yang juga didirikan oleh Kapitan Bong.
Aroma Hio menyambut kami. Nur Zen Hae, Risa Syukria, Kedung Darma Romansah, dan Dahlia, mencoba bergantian mengadu peruntungan dan ramalan nasib dengan membakar Hio di depan patung Thai Pak Kong (Paman Besar) bernama Liang San Phak dan patung istrinya, yang dibawa langsung oleh Kapitan Bong dari negeri leluhurnya. Patung ini pada tanggal 15 bulan ketujuh penanggalan Cina, diarak mengelilingi kota Belinyu sebagai prosesi sembahyang rebut.
“Ini Klenteng Dewa Bumi atau Tapekong. Menurut agama Konghucu, Klenteng Tapekong ini untuk tempat bersembahyang dan meminta agar rezeki banyak dan keselamatan,” ujar Fujianto alias Afu (35), salah seorang pengurus Klenteng.
Saya ingin bertanya lebih banyak lagi pada Afu yang ramah itu. Tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, perjalanan musti dilanjutkan.
Pha Kak Liang
Setelah melewati jalan tanah berdebu, dan sesekali bertemu pula dengan bekas tambang timah yang ditinggalkan, sampailah kami di gerbang utama Pha Kak Liang yang bernuansa Cina. Makin ke dalam, arsitektur Cina itu makin terasa. Seperti demarga, rumah peristirahatan, gazebo, semuanya berornamen Cina.
Pha Kak Liang adalah sebuah objek wisata tirta yang dibangun di atas bekas tambang timah (kolong). Terletak 10 Kilometer dari kota Belinyu.
Keheningan dan kedamaian begitu terasa di tepi telaga seluas 3,5 hektar yang ditumbuhi pohon cemara dan akasia. Pemiliknya tiga orang etnis Cina bersaudara, dan menjadikannya sebagai villa peristirahatan, yang tetap terbuka untuk umum.
Sayangnya, kurang terawatnya Pha Kak Liang membuat objek wisata degan telaga berisi ribuan ikan emas yang hidup bebas itu tampak sedikit suram. Tapi bagi pecinta suasana sunyi, Pha Kak Liang memberikan itu. Dan semakin lama akan makin terasa.
Namun, lagi-lagi perjalanan musti dilanjutkan.
Pantai Penyusuk
“Lihat pohon-pohon yang memeluk batu itu!” ucap Raudal.
Kalimat Raudal yang puitis itu seperti memberi tahu bahwa kami telah memasuki gerbang pantai Penyusuk. Ya, di kiri-kanan jalan memasuki area pantai tampak beberapa batu besar yang di sekilingnya di tumbuhi pohon-pohon.
Hamparan pantai yang landai dan ditumbuhi batu-batu besar menyambut kami. Beberapa perahu nelayan tertambat. Ombaknya tenang karena di depannya ada pulau cukup besar yang menjadi tameng. Sedang pulau kecil di sampingnya, berdiri menara suar yang tampak sebesar pohon nyiur melambai dari tempat saya berdiri.
Amboi! Negeri rayuan pulau kelapa, alangkah eloknya.
Saya tidak sabaran ingin menceburkan diri. Mandi-mandi di laut jadi kanak-kanak ria kembali. Hilang sejenak segan pada usia.
Namun Risa Syukria meminta saya untuk menemani dia mengambil air wudhu. Inilah perkaranya, ternyata kamar mandi umum dikunci. Penjaganya entah kemana.
Memang pantai Penyusuk sepi, jauh dari pedagang yang mata duitan. Akhirnya, kami menemukan berbungkus-bungkus air minum tergeletak ditinggalkan pemiliknya di atas sebuah batu besar.
Jadilah Risa sholat dan saya pun mandi menceburkan diri ke laut menyusul yang lain, yang telah dulu bermain dengan air garam yang jinak itu. Tak lama berselang, Risa pun menyusul.
Cuma Kedung Darma Romansah dan Pak sopir yang tidak mau membasahi tubuhnya dengan air laut di pantai yang tenang itu. Entah kenapa.
Setelah puas mandi-mandi. Main pasir pantai yang putih. Duduk-duduk dari satu batu ke lain batu. Rombongan sastrawan itu memutuskan untuk pulang.
Matahari sudah mulai mendekati ubun-ubun laut, beberapa jam lagi bakal angslup. Cuaca cerah. Tentu saja sunset akan terlihat terlihat sempurna di pantai barat ini. Namun apa hendak dikata, pertemuan matahari dan laut yang menciptakan cahaya emas itu, tak bisa saya saksikan.
Kami pun pulang dengan tubuh yang belum dibilas dari air laut karena penjaga kamar mandi umum itu tidak juga datang.
Sesampai di jalan Depati Amir, saya dan Risa Syukria yang juga reporter TV Siak, memutuskan turun dari mobil. Kami ingin berjalan kaki berdua menuju rumah Sunlie di jalan Sriwijaya yang jaraknya sekitar 500 meter dari tempat kami turun. Sedang yang lain terus pulang dengan mobil.
Kami turun dari mobil itu bukan karena ngambek, tapi ingin melihat lebih dekat rumah-rumah arsitektur Belanda yang dihuni pegawai timah di bawah gelimang cahaya senja.
Ya, sepanjang jalan Depati Amir itu berjajar bangunan-bangunan lama. Sayang sebagian sudah tidak terawat lagi. Padahal bangunan-bangunan itu merupakan jejak langkah dari perjalanan kota timah itu.
Menurut Ibrahim (52) salah seorang karyawan pertambangan timah yang kami temui di salah rumah kuno itu, dulunya rumah-rumah di kawasan jalan Depati Amir itu adalah kawasan elit yang ditempati oleh pegawai teras atas pertambangan timah. Dibangun pada tahun 1928.
Namun sejak menipisnya cadangan timah di Belinyu, rumah-rumah itu dihuni campur aduk antara karyawan biasa dan pegawai menengah. Bahkan sebagian rumah tidak dihuni lagi dalam kondisi yang mengenaskan, pintu dan jendela yang copot, serta dindingnya kumuh penuh coretan.
“Kota yang aneh. Tidak seperti kota-kota lain yang pernah saya datangi. Selama di sini, belum pernah saya lihat ada ABG nongkrong bersama menghabiskan petang. Bagaimana ya orang-orang hidup dalam kelengangan ini?” ucap Risa, dara rancak asal Minang ini, di jalan menuju ke rumah Sunlie—selepas jalan Depati Amir.
“Kota ini membuat Ngai Oi Ngi!” ujar saya memakai sekerat bahasa Hakka yang saya pelajari dari Sunlie.
“Apa itu Ngai Oi Ngi?” tanya Risa.
“Aku Mencintaimu!”
Saturday, August 8, 2009
Sajak dari Lirik Lagu Kahitna
Sajak yang Ditulis dengan Sangat
Terburu-buru Sebab Aku Harus
Menyelesaikannya Sebelum Lagu
Kahitna itu Selesai Dinyanyikan
ENGKAU tak bisa membedakan Hedi dan Carlo,
apalagi suara Mario, bukan? Dia vokalis
yang menggantikan Roni, tapi itu tak perlu!
Dengarkan saja kalimat-kalimat liriknya
sejak bair pertama: Tak ada Yang harus
kita sesali. Semua indah yang pernah
kita alami....
Engkau setuju? Yovie adalah lirikus terbaik
di negeri ini, bukan? Oh, ya tentu, tentu,
kau harus menyejajarkannya dengan Katon.
Atau Ebiet? Ha ha, terlalu beratkah dia
buatmu? Atau terlalu sastra? Lupakan dulu!
Simak itu, lirik pada bait kedua: Meskipun
terbatas dan tak mungkin terikat janji
abadi.
Ah, aku tak yakin, apakah benar aku tidak
pernah bercerita pada Yovie, tentang kau
dan aku (dan dia)? Kenapa lirik di lagu
ini seperti ia tahu rahasia-rahasia panas-api
dalam kering-sekam kita? Dan bait ini: Aku,
dirimu, dirinya tak akan pernah mengerti
tentang suratan ... bukankah teramat kita?
Sebentar, ikuti aku menyanyikan juga bagian
lirik berikutnya. Hmmm, tak perlu menyesuarakan
suara kita dengan para vokalis padu itu, hayati
saja kata-katanya:... Aku, dirimu, dirinya tak
resah bila sadari, cinta takkan salah.. Tapi,
kenapa aku resah? Kenapa aku selalu percaya
bahwa cinta kita ini salah?
Aduh, aku tak tahu lagi itu Hedi, Carlo atau Mario,
aku bayangkan itu adalah suaraku sendiri, yang
seperti anjing kesunyian, melolong jeritan: Andai
waktu bisa kita putar kembali, jalinan cerita
mungkin tak begini...
Halo? Engkau masih adakah, saat selesai kutuliskan
sajak yang sangat terburu-buru ini? Halo, engkau?
Catatan:
Teks yang diitalikkan adalah syair lagu Kahitna
"Aku, Dirimu, Dirinya" dari Album "Soulmate" (2006)